White Room
Oleh: Vianda Alshafaq
Kedua lenganku diapit oleh dua orang laki-laki bertubuh besar dan kekar. Wajah mereka datar dan kaku, seperti tembok. Tanganku diborgol dan beberapa kamera menjepretku dari depan. Entah untuk apa mereka mengambil gambarku, aku tidak mengerti. Dan, aku juga tidak tahu mereka akan membawaku ke mana sebenarnya.
Pagi tadi, mereka menerobos masuk ke dalam rumah. Saat itu, kami—keluargaku dan aku—sedang sarapan pagi. Tepat saat aku akan memasukkan gigitan kedua dari roti yang menjadi menu sarapan, orang-orang itu sampai di ruang makan kami. Mereka tiba-tiba menodongkan pistol. Ibuku menjadi histeris seketika. Ia berteriak-teriak meminta pertolongan. Tapi, hal itu sungguh tak berguna. Ruangan makan ini terletak di bagian belakang rumah, jauh dari pintu depan. Aku tidak yakin ada orang yang akan mendengar teriakan itu walau Ibu berteriak setengah mati.
Ibu menyerah. Mungkin tenggorokannya sudah sakit. Atau karena dia sudah paham bahwa hal itu hanya sia-sia saja. Entahlah.
Tanpa aba-aba dan perkataan apa pun, salah seorang dari laki-laki itu berjalan ke arahku dan tetap menodongkan pistolnya. Sebenarnya, apa mau mereka?
“Ikutlah dengan kami. Dan, kami tidak akan mengganggu keluargamu.”
Pria itu tepat berada di depanku, hanya berjarak sekitar dua langkah.
“Aku tidak mau.” Setengah mati aku mencoba untuk tetap tenang dan tidak memperlihatkan rasa takut yang sebenarnya sedang menjalar di seluruh tubuhku.
Tiba-tiba, laki-laki yang lain menjambak rambut ibuku. Oh, Tuhan, aku tidak sanggup melihatnya. Ibuku meringis kesakitan sembari memegang rambutnya agar tak tertarik semakin kuat.
“Jika kau tidak ikut, kau akan melihat mereka terbunuh saat ini juga.”
Aku melihat ke arah Jhon, adik laki-lakiku yang sedikit berbeda dari anak-anak lainnya. Umurnya lima belas tahun tapi ia masih seperti anak-anak berusia di bawah sepuluh tahun. Dan, sejak tadi ia meringkuk ketakutan, bahkan tubuhnya gemetaran. Meski bukan adik kandungku, aku sangat menyayanginya. Aku tidak kuat melihat ia ketakutan seperti itu.
“Kenapa aku harus ikut denganmu?”
“Karena kami diperintahkan untuk menjemputmu.”
“Oleh siapa? Dan, kenapa dia menyuruhmu menjemputku?”
Aku sungguh tidak tahu mengapa orang-orang ini menginginkan diriku. Dan, aku juga tidak tahu siapa yang menginginkanku. Kurasa, selama ini aku tidak mengganggu siapa pun. Dan, aku tidak memiliki musuh.
“Kau akan tahu setelah kau ikut.”
***
Mobil berhenti di suatu tempat yang tidak kukenali. Letaknya sangat jauh dari jalan raya. Yang ada di depanku hanya sebuah rumah berwarna abu-abu sederhana yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi dan rimbun. Angin sepoi-sepoi mengembus ujung gaunku. Sejuk. Tempat ini sangat sejuk.
Dua laki-laki tadi kembali berjalan. Mereka membawaku ke dalam rumah itu. Tepat saat pintu dibuka, aku melihat seorang laki-laki berjas hitam yang duduk di sofa dan membelakangiku. Di sekitarnya berdiri beberapa pria dengan jas hitam dan tubuh besar, seperti dua laki-laki yang sedang mengapit lenganku.
Dua laki-laki itu menjatuhkanku tepat di depan laki-laki yang kutebak sebagai bosnya. Salah satu dari mereka menekan kepalaku sehingga posisiku seperti menunduk pada laki-laki tadi. Oh, Tuhan, sebenarnya siapa mereka?
Samar-samar, aku melihat laki-laki itu mengangkat tangannya, membuat para pria selain dirinya meninggalkan rumah ini. Aku mengangkat wajah. Mencoba mengenali wajah itu dan mencari ingatan tentangnya di kepalaku. Tapi, tak ada satu pun yang bisa kuingat tentang dia. Kemungkinan besar aku memang tidak kenal siapa laki-laki ini.
“Kau pasti sangat terkejut pagi ini, Nada.”
Aku hanya diam, tidak ingin mengatakan apa pun ataupun menatap wajahnya.
“Tapi itu bukan masalah. Sekarang semuanya akan kembali baik, jika kau mengatakan yang sebenarnya padaku.”
“Aku tidak mengerti apa yang kau katakan.”
“Ayahmu. Di mana dia?” tanya laki-laki itu lagi.
Jadi, sebenarnya laki-laki ini mengincar ayahku?
“Kurasa seluruh dunia sudah mengetahui fakta bahwa ayahku sudah tiada.”
Dia tersenyum kecut, seperti meremehkanku. Sepertinya dia tahu bahwa ayahku masih hidup. Sebab itulah ia saat ini menahanku. Tapi bagaimana ia mengetahuinya?
“Kau bisa membohongi dunia. Tapi bukan aku. Jadi, jawablah dengan benar sebelum aku menghancurkanmu dan kau tidak akan pernah lagi bertemu dengan laki-laki tua itu.”
“Kau bisa membunuhku jika kau mau. Tapi sampai helaan napas terakhir, aku tidak akan pernah mengatakan keberadaan ayahku.”
Ternyata, masih ada orang-orang yang mencari ayahku. Ayahku sebenarnya hanya seorang ahli kimia yang biasa-biasa saja, bukan ilmuwan besar. Hanya, sebelum ia meninggalkan aku dan keluargaku, ia menemukan sesuatu. Aku tidak tahu apa yang ia temukan. Hanya saja, ia bilang itu adalah sesuatu yang berbahaya untuk dunia. Ia tidak menjelaskan detailnya seperti apa.
“Kau serius ingin melindungi laki-laki tua itu?”
“Apa yang kau cari sebenarnya?” tanyaku memberanikan diri.
“Kau sudah tahu, kenapa masih bertanya?”
“Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Dan, aku juga tidak akan berbicara lagi.”
Laki-laki itu menamparku. Rasanya sangat perih. Pipiku memanas dan sepertinya memerah. Sudut bibirku terluka, darah segar mengalir dari sana. Aku hanya memejamkan mata, menetralisir rasa perih yang masih menjalar itu.
Laki-laki itu masih bertanya. Sepertinya ia sangat ingin mengetahui keberadaan ayahku. Sejujurnya, aku tidak tahu kenapa aku harus melakukan semua ini—diam dan tak berkutik sama sekali. Sebelum pergi, Ayah memberitahuku ke mana ia akan pergi dan kapan ia kembali. Ia tidak mengatakan kenapa ia pergi dan menghilang seperti ditelan bumi. Waktu itu Ayah juga memintaku berjanji bahwa sampai kapan pun aku tidak akan pernah mengatakan kepada siapa pun tentang dirinya. Yang boleh diketahui dunia adalah kebohongan bahwa ia sudah tiada. Ia meyakinkanku untuk tetap tutup mulut karena sesuatu yang ia coba musnahkan itu sangat berbahaya untuk dunia. Tapi, sungguh, sekali pun ia tidak pernah mengucapkan apa itu. Bahkan, setelah beberapa tahun ia pergi, aku mencoba mencari tahu melalui internet. Tapi, aku tidak menemukan apa pun.
Tiga tamparan sudah mendarat di pipiku. Laki-laki itu semakin marah sebab aku tak juga berbicara. Ia memanggil anak buahnya yang kemudian diperintahkan untuk membawaku. Laki-laki itu menarikku dengan kasar. Mereka membawaku ke bagian belakang rumah. Yang kulihat hanyalah dinding berwarna putih dan sebuah pintu yang juga berwarna putih.
Aku dimasukkan ke dalam ruangan kosong itu. mereka mengunci pintu dari luar dan meninggalkanku sendirian di tempat sunyi itu. tidak ada suara apa pun. Bahkan dentingan jarum jam tidak bisa kudengar.
Ruangan ini benar-benar kosong. Tidak ada apa pun selain dinding putih, plafon putih, lantai putih, dan lampu putih. Tidak ada jendela, tidak ada ventilasi. Benar-benar seperti kubus putih tanpa celah kecuali sedikit ruang di bawah pintu—sepertinya tak sampai sesenti.
Aku duduk di sudut ruangan. Mengetukkan jariku di lutut. Aku tidak tahu pergerakkan waktu. Tidak ada yang bisa kuketahui selain ruangan serbaputih ini. Sialnya, aku juga menggunakan gaun putih. Seandainya aku tahu, aku tidak akan memakai gaun putih hari ini.
Sejujurnya, aku tahu apa yang sedang dilakukan pria itu. Dia benar-benar ingin menghancurkan diriku. Aku memahami apa yang terjadi setelah aku keluar dari tempat ini—itu pun jika aku masih bisa keluar dan tidak mati di sini.
Rasanya sudah lama aku berada di sini. Tiba-tiba pintu dibuka. Salah satu dari orang suruhan laki-laki tadi datang dengan berpakai serbaputih dengan sepiring nasi putih yang juga ditaruh di piring putih. Oh, Tuhan, laki-laki itu benar-benar menghukumku.
“Lebih baik kalian membunuhku daripada melakukan hal ini. Aku tidak ingin gila.”
Laki-laki itu hanya menatapku tanpa berbicara satu kata pun, kemudian menutup pintu lagi.
Mereka menggunakan metode White Room untuk menghukumku. Ini bukan penyiksaan fisik, tetapi penyiksaan psikologis yang secara pelan-pelan akan membuatku mati tetapi tetap hidup. Aku pernah membaca hal ini di sebuah artikel. Hukuman ini akan membuatku ketakutan dan kehilangan fungsi dari beberapa indraku.
“Sungguh, lebih baik aku mati daripada berada di tempat seperti ini!”
Aku melihat piring yang tadi diantarkan oleh pria itu. dengan segera, aku membuang nasi ke lantai dan mengempaskan piring itu. seperti keinginaku, piring itu pecah. Aku mengambil salah satu pecahannya yang runcing.
“Ibu, Jhon, Ayah, maafkan aku. Lebih baik aku mati daripada disiksa di tempat ini. Semoga kalian selalu bahagia.”
Itu kalimat terakhir yang kuucapkan. Setelahnya, aku menyayat pergelangan tanganku, tepat di bagian urat nadi. Darah segar mengalir dari sana. Rasa perihnya menjalar hingga ke ubun-ubun. Aku menyayat tangan berkali-kali. Meski sangat kesakitan, ini lebih baik daripada aku harus tersiksa di tempat ini.
Tidak tahu sampai kapan aku terbaring dengan darah yang terus mengalir. Bahkan gaunku yang putih berubah warna menjadi warna darah. Setelah cukup lama dalam keadaan terluka parah, aku tidak lagi melihat warna putih. Aku tidak lagi melihat apa-apa. [*]
Vianda Alshafaq, seseorang yang bukan siapa-siapa.
Editor: Fitri Fatimah

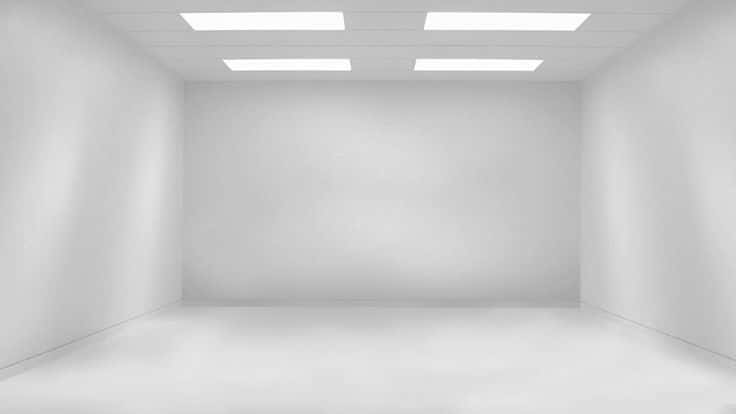



9 thoughts on “White Room”