Nada Sendu
Oleh : Alisa Davina
Andai hidup semudah melodi musik di pesta, sudah pasti aku tak merasa menderita.
“Mbak Is, sini! Ibu ada penting ama sampean,” panggil Ning Nisa di emperan ndalem.
“Siap, Ning. Aku ke sana.” Aku yang sedari tadi duduk termangu di teras balai pondok usai mengajar, lantas bangkit, lalu masuk ke istana cantik bergaya minimalis itu.
Bu Nyai terlihat khusyuk di sofa sambil melantunkan ayat-ayat Al-Qur’an.
Kuucap salam penuh takzim. Beliau mempersilakanku duduk di atas busa berwarna marun itu, tapi aku lebih memilih duduk di lantai, sungkan.
“Ada apa geh, Bu?” tanyaku penasaran.
“Anakku yang bungsu baru pulang dari Yaman, dia ingin taaruf sama sampean,” terang Bu Nyai.
“Alhamdulillah. Inggih, Bu.”
“Le, ke sini.” Bu Nyai memanggil sesosok yang berada di ruang tengah keluarga, di bilik kelambu biru.
Tampak ia melangkah ke arahku. Lalu, aku segera menunduk karena malu. Payah.
“Angkat wajahmu, Mbak,” perintah wanita paruh baya itu memecah keheningan.
Deg.
Mata kami bertemu. Seperti terhujani ribuan bunga yang turun dari langit. Mata cokelatnya, postur tegap gagah itu, dan hidung mancung ala orang Arab. Subhanallah.
Lima detik. Dunia seperti berhenti sejenak.
Cepat-cepat kami mengalihkan pandangan satu sama lain. Ada debar-debar di hati.
Mengobrol sedikit dengan ditengahi Bu Nyai, lelaki yang duduk di sebelah ibunya itu sering menimpali percakapan dengan sedikit kata, sama sepertiku. Lalu, aku undur diri karena jarum jam menunjukkan pukul sembilan malam. Dan keputusan perjodohan ini, tiga hari lagi.
***
Pagi.
Di toko. Usai mengatur dan mengecek beberapa kepingan kaset musik juga film, aku duduk di belakang etalase sembari membaca Al-Qur’an. Meski tempatku bekerja jarang dikunjungi orang karena tergerus dengan perkembangan zaman modern, tapi di sinilah aku bisa bekerja sambil melancarkan hafalan. Sesekali melihat ponsel jika ada notifikasi masuk. Berselancar di dunia maya. Tertawa kecil untuk mengatasi rasa jenuh.
Sebuah chat datang. Tertulis nama “Ibuku, Nyai Hasanah”.
Assalamu’alaikum.
Wa’alaikumsalam, Bu.
Maafkan kami sekeluarga, ya, Mbak.
Ada apa, Bu?
Dini hari tadi, kerabat kami dari Bandung mengabari kalau Yai Shofyan sedang kritis karena kecelakaan. Jadi beliau punya keinginan terakhir untuk menikahkan Zainal dengan putri bungsunya, sesegera mungkin di hadapan beliau. Kami sekarang sedang dalam perjalanan.
Seperti disambar petir di siang bolong, lemas. Kuketik dengan berat hati.
Yaa Alloh … ya, Bu. Ndak apa-apa.
Mbak Is. Maaf … maaf … maafkan kami.
Ndak, Bu. Aku ikhlas, demi Alloh.
Maturnuwun, Mbak Is. Semoga Gusti memberi sampean ganti yang lebih baik. Semoga Alloh memberimu barokah di dunia akhirat.
Aamiin … aamiin … aamiin. Sama-sama, Bu. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas doanya. Doa terbaik untuk jenengan sekeluarga.
Insyaallah, kami akan berkunjung ke rumah sampean nanti untuk silaturahmi dan meminta maaf secara langsung.
Bingung harus jawab bagaimana. Kutatap lalu lintas kendaraan, hampa.
Tak berselang lama, masuk satu pesan panjang dari nomor asing.
Assalamu’alaikum. Untuk bidadari surgawi. Aku yakin panggilan itu akan tersemat untukmu kelak. Meski bukan aku yang akan menggandeng tangan manismu untuk bersama-sama melangkah ke surga-Nya. Sungguh, rasa ini ingin memiliki. Tapi apalah daya, demi taat ini pada orangtua. Semoga kau ikhlas menerima. Tetaplah menjadi bunga yang semakin hari semakin harum. Jangan sampai satu kumbang menyentuh indahmu sebelum waktu yang tepat. Semoga kita tetap di jalan yang benar dan lurus, shirothol mustaqiim. Wassalamu’alaikum.
Lemah. Ingin menangis, tapi air mata kering sudah.
Kuletakkan gawai kembali. Berdiri mengambil VCD kesukaanku, lalu menyetelnya.
Sebuah lagu dari Opick, Rapuh.
Meski kurapuh dalam langkah
Kadang tak setia kepada-Mu
Namun cinta dalam jiwa
Hanyalah pada-Mu
Maafkanlah bila hati
Tak sempurna mencintai-Mu
Dalam dada kuharap
Hanya diri-Mu yang bertakhta
Detik waktu terus berlalu
Semua berakhir pada-Mu
Gerimis pagi ini mengiringi senduku yang entah … bagaimana aku bisa melukiskannya.
Tak sadar. Ternyata ada seorang nenek yang berteduh di emperan toko.
“Sini, Mbah. Di dalam, nggak apa-apa!” Aku menepuk pundaknya, dengan ragu ia kutuntun masuk dan duduk di sampingku.
“Boleh minta air, Cu?” kata wanita berpakaian compang-camping itu.
“Tentu, Mbah. Kubuatkan minuman penghangat malah.”
Lalu, aku ke dapur untuk membuat dua cangkir teh. Kembali lagi ke depan, bersama wanita tua renta itu menikmati setiap seduhannya.
Bagiku hidup layaknya seni. Seperti melodi dalam sebuah lagu. Menyimpan nada penuh kenangan, bahagia, juga derita.(*)
Editor : Lily
Grup FB KCLK
Halaman FB Kami
Pengurus dan kontributor
Mengirim/Menjadi penulis tetap di Loker Kata

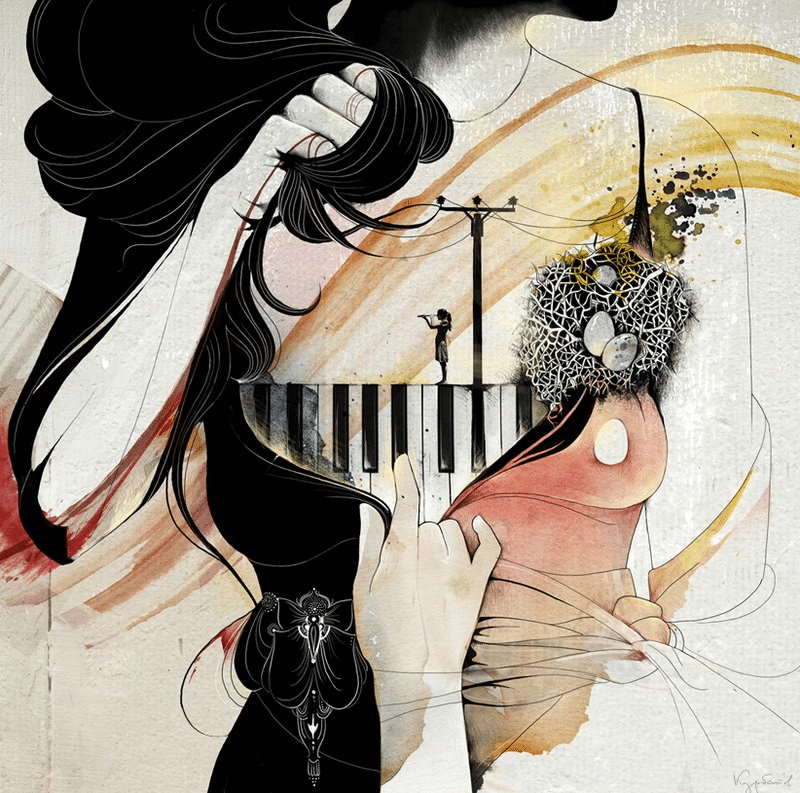



7 thoughts on “Nada Sendu”