Lantak
Oleh : Pipit
1.
Seorang anak kecil pulang tergopoh-gopoh. Bajunya basah, badannya bau lumpur, kakinya berkerak tanah. Ia berjinjit pelan menuju kamar mandi hendak membersihkan diri. Namun, belum sampai ke tujuan, bocah lelaki itu terpeleset. Badannya jatuh di lantai rumah panggung tua sederhana peninggalan Dayat, hingga menimbulkan gaduh penghuni yang lain.
“Sudah Mak cakapkan, *dak usah main ke tepi sungai. Masih lagi,” gerutu ibunya yang membiarkan si bocah bangkit sendiri.
Ayahnya melirik sebentar, menggeleng beberapa kali, lalu kembali asyik menonton televisi yang menayangkan sejumlah daerah yang terkena banjir.
“Ayah, aku dapat ini.” Bocah lelaki tadi sudah mandi, wangi sabun masih melekat di tubuhnya. Dengan senyum semringah, ia duduk di samping ayahnya memperlihatkan sebuah pelampung pancing berbentuk hiu kecil.
2.
“Eh, Dayat. Tak kerja kau?” Suara Wak Saleh datang bagai memagar kesedihan. Respons apa yang harus ditunjukkan Dayat, kenapa lelaki itu tampak biasa saja tanpa rasa bersalah sedikit pun? Bukankah sudah sering didengarnya orang-orang membicarakan alasan Dayat diberhentikan kerja, yang tidak lain dan tidak bukan karena Wak Saleh merasa terusik oleh sikap Dayat.
Kepada Wak Saleh, lelaki berusia 45 tahun itu pernah bercerita soal anak sungai, yang induknya terpanjang seperti ular raksasa membelah di pulau Sumatera itu tidak seperti dulu. Airnya keruh semacam lopak disebabkan sungai semakin dangkal. Bila musim hujan tiba air mudah meluap lalu banjir tak bisa terelakkan. Ditambah lagi sampah plastik bertebaran di sepanjang aliran sungai. Hati Dayat teriris, mengadu kepada Wak Saleh. Sebagai orang yang punya kekuasaan terhadap penambangan emas ilegal kelas teri, Wak Saleh punya hak untuk mematikan pekerjaan itu. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, Dayatlah yang kehilangan pekerjaan. Ia dipecat tanpa alasan yang jelas, seperti mengada-mengada, kurang disiplin katanya, karena beberapa minggu yang lalu ia pernah terlambat beberapa menit saat masuk kerja.
Dayat tersenyum. “Saya dipecat, Wak,” jawabnya ringan.
“Dipecat pasti ada sebabkan?”
“Mungkin sebatas itu rezeki di sana.”
“Oh, Dayat. Tak semudah itu memecat karyawan teladan macam Awak, nih. Proteslah.”
Dayat enggan menjawab. Seulas senyum ia berikan kepada Wak Saleh. Meskipun hatinya masih menyisakan bara-bara kecil yang belum padam sepenuhnya.
3.
Setelah kematian istrinya, Dayat lebih banyak menyendiri, duduk sendiri di tepi sungai, di bawah pohon rindang sambil memainkan mata pancing yang dibawanya dari rumah. Berbeda dengan kemarin-kemarin, hari ini sudah hampir tiga jam ia menunggu, tapi umpannya tak jua disambar ikan. Keresahan mulai menghampiri Dayat, jumlah ikan yang berkurang, atau memang dirinya yang tak pandai memancing. Rasa-rasanya tak ada yang salah dengan caranya melemparkan senar mata pancing, tetapi sayangnya jangankan induk patin, anak seluang pun tak mau menyentuh umpannya sampai senja memerah, lalu menua menyambut malam, Dayat pulang dengan tangan kosong.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali sepulang dari mengantar kedua anaknya sekolah, Dayat menyendiri lagi di tepi sungai. Berharap ketenangan pagi ini tidak sesial kemarin sore. Maka, bersama pancing dan segala peralatan yang dibawa. Kali ini, ia memilih jauh ke hilir sungai, duduk seorang diri. Udara pagi terasa lebih segar ketika umpan pertama dilempar. Sayangnya, suara bising dari mesin-mesin pendulang emas memecah ketenangan Dayat. Yang terkadang sulit dibedakan; apakah ia sedang mengenang almarhum istrinya, atau memang memancing adalah hobi barunya. Yang membuatnya tetap menyenangi, meskipun pulang tanpa membawa seekor ikan pun.
“Abang, sampahnya jangan dicampur,” kata istrinya sambil tetap merajut. Tiba-tiba saja kenangan dengan istrinya datang melesat, hanya karena sampah plastik masih terapung-apung di tepi sungai, tak jauh dari tempatnya, sepertinya sampah itu baru saja dibuang. Dan Dayat pada saat itu tak membantah, istrinya memang teliti mengolah sampah rumah tangga. Dan malam itu, Dayat yang sehabis menonton pertandingan sepak bola mencampur-adukan sampah plastik camilannya dan kulit buah pisang dalam satu tempat. Dan perbuatan itu haram hukumnya bagi almarhum sang istri.
Bagi istri Dayat yang pernah menjadi anggota dasawisma, sampah rumah tangga pun bisa menjadi ancaman kerusakan alam, bila tidak ada kesadaran tiap buah rumah dalam pengelolaannya. Dan perannya sebagai ibu rumah tangga, sudah sepatutnya bertindak meskipun dari hal-hal kecil. Seperti kulit buah dan sayur-sayuran sisa memasak yang dibuatnya kompos, dan nantinya dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman sayuran yang saban hari dirawatnya. Meskipun hanya hitungan jari di pekarangan rumah. Sedangkan sisa kaleng minuman, botol plastik, kardus, perempuan itu menjualnya ke tukang rongsokan.
“Tak apa, Abang. Adik tak merasa repot. Hanya butuh waktu menjadi kebiasaan,” kata perempuan itu, ketika Dayat menawarkan diri untuk membantu membuang sampah agak jauh ke tanah kosong milik salah satu warga. Di sana sampah tidak dibiarkan begitu saja. Ada petugas yang mengangkut dan membawa sampah-sampah itu ke tempat pembuangan akhir. Sayangnya, tidak banyak warga yang mau repot-repot mengantarkan ke sana. Dan lihat! Mereka lebih memilih membuang sampah ke sungai. Lebih praktis katanya.
Wajar saja hati Dayat mendadak nyeri melihat sampah plastik yang terapung-apung itu, yang seolah sedang mengejeknya. Menertawakan kebiasaan istrinya yang kini terlanjur menularinya. Ah, andaikan semua istri sepanjang aliran sungai ini sama-sama peduli lingkungan seperti istrinya.
4.
Di pos ronda simpang tiga, di malam Minggu, sepulang dari tahlilan tujuh hari salah satu warga, untuk ke sekian kali Dayat menyampaikan keberatannya dengan warga setempat, bahwa penambangan emas ilegal makin merajalela, dan tak bisa didiamkan.
“Kasihan sungai kita, Pak RT,” kata Dayat memulai ke pokok permasalahan.
“Lebih kasihan lagi anak bini kita, Yat,” sela yang lain.
“Iya, kau bercakap macam itu karena kau kerja di pabrik, sedangkan kita?” protes dari yang lain.
Dayat bungkam lagi. Memang betul kata orang kebutuhan perut lebih utama, setelah kenyang barulah dapat berpikir tentang hal lain. Kurang lebih begitulah hasil yang didapat Dayat malam itu. Siapa yang peduli dengan nasib lingkungan puluhan tahun ke depan. Tak ada. Bahkan sekelas aparat tentara yang ditemuinya juga tak memberikan jawaban pasti. Pun dengan orang-orang kelurahan, tutup mata adalah pilihan tepat. Padahal Dayat sangat meyakini, mereka semua tahu yang mana hitam mana putih. Namun, nikmatnya suapan dari Wak Saleh yang sebagai kaki-tangan dari ‘orang atas’ mereka memilih diam. Tak ada yang berani menentang. Orang yang berkuasa di kampung ini adalah pemilik uang.
Sebab itu, pada malam Rabu yang kelabu, Dayat bertandang ke rumah Wak Saleh. Mengetuk pintu hati lelaki berusia 65 tahun itu, dengan sejumlah kata manis bercampur miris. Barangkali Wak Saleh tergugah, sejalan dengan harapannya.
“Kau tahu kan, mencari pekerjaan sekarang susah,” kata Wak Saleh. “Orang-orang penambang itu tak ada pilihan lain. Kalau kau ada kerja untuk mereka, malam ini juga aku berhentikan.”
Merah padam muka Dayat. Tak berdaya dengan tantangan Wak Saleh. Untuk ke sekian kali upayanya terasa sia-sia saja. Hingga Dayat pun sadar, puluhan hari setelah kelancangannya yang repot-repot mengurus penambangan emas ilegal itu kini membuatnya kehilangan pekerjaan.
5.
Lelaki yang dipanggil ayah itu duduk termangu sebentar, lalu beranjak ke kamar paling belakang diikuti si bocah. Di sana keduanya memasangkan pelampung pancing berbentuk hiu kecil, yang warnanya telah mengusam milik Dayat, ayah si lelaki itu.
“Oh, ini punya datuk, Nak. Pas ‘kan?” Bocah itu mengerjap. Sementara ingatan lelaki itu kembali ke masa lalu, di mana ayahnya dipaksa menyerah oleh keadaan lalu menghabiskan masa tua dengan pancing-pancing kesayangannya di tepi sungai.
Di luar kamar, televisi masih menyala, pembaca berita belum selesai melaporkan sejumlah daerah yang terkena banjir.
Jambi, 26 September 2024
*Dak = Tidak
Pipit, perempuan yang sedang belajar menulis.

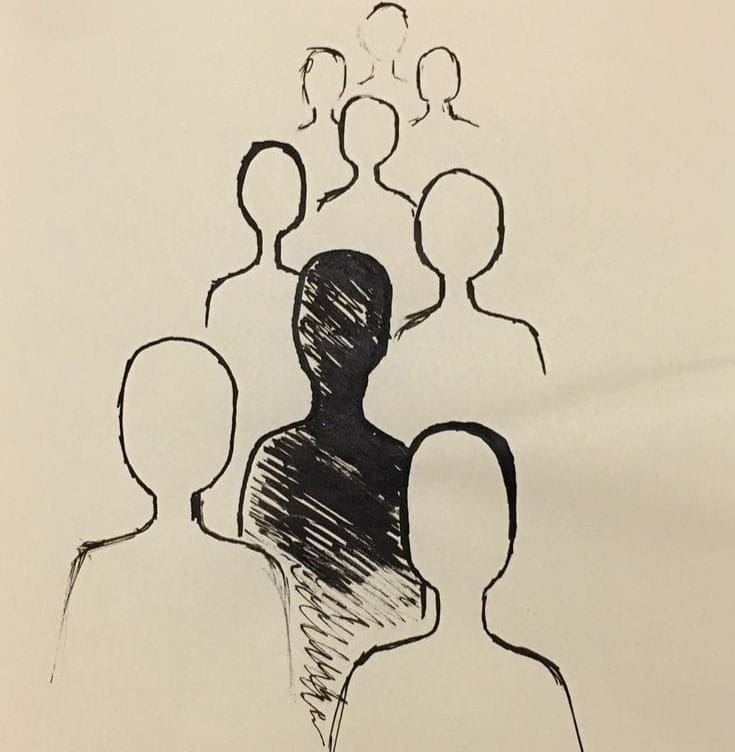



9 thoughts on “Lantak”