Kayu Manis dan Buah Persik
Oleh: Carissa Maharani
Jam sudah menunjukkan waktu makan malam, namun Ardan masih duduk di ruang kerjanya, di lantai delapan. Hanya tinggal beberapa pekerja yang masih tersisa, karena mengambil jam lembur dan masing-masing dari mereka tengah fokus ke pekerjaannya. Suara televisi menjadi satu-satunya sumber suara di ruangan Ardan. Ardan tidak begitu memperhatikan. Ia hanya butuh itu, sebagai sesuatu untuk menemaninya.
Ardan menatap ponselnya. Ada pekerjaan yang harus ia kumpulkan besok, namun ia belum juga mendapatkan solusi untuk kesulitannya. Lima tahun sudah Ardan bekerja sebagai jurnalis, hingga akhirnya ia dapat menjadi ketua divisi, baru kali ini, ia bingung dengan apa yang ia hadapi.
Pelukis ternama yang belasan tahun terkenal, menggelar pameran galeri terakhirnya. Tentu itu berita cukup besar di kota tempat ia tinggal, karena hampir seluruh masyarakat dari berbagai generasi mengetahui hasil karya terbaik pelukis tersebut. Lukisan kayu manis dan buah persik.
Lukisan itu dibuat 18 tahun lalu, dan lukisan itulah yang membuat beliau dikenali semua orang di kota. Ahya To namanya. Beliau seorang pria berumur 53 tahun, tetapi perawakannya terlihat lebih tua dan beberapa kali juga beliau divonis penyakit berbahaya. Untungnya, beliau tetap sehat sampai sekarang meski jalannya sudah dibantu tongkat.
Ardan, yang merupakan jurnalis terbaik perusahaannya, dipanggil khusus oleh Ahya To untuk wawancara. Ya, kesempatan yang sangat spesial. Ahya To tidak pernah menerima tawaran wawancara selama 18 tahun karirnya. Alasannya, selalu sama. Ia tidak pandai berbicara di depan orang lain bahkan orang terdekatnya.
Sebenarnya, Ardan senang mendapatkan kesempatan itu. Perusahaannya pun mendukung penuh wawancara tersebut. Tak bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akan membaca artikel wawancaranya dan pastinya akan menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan.
Bayangkan saja, 18 tahun Ahya To berkarya, tak pernah sekalipun ada satu momen beliau berbicara depan umum, meski demikian, ia tetap terkenal. Eksistensi lukisan-lukisan yang diciptakannya seperti bensin bagi api. Galeri hasil karyanya sampai sekarang masih jadi salah satu tempat legendaris di kota. Bahkan pernah beberapa kali dikunjungi turis mancanegara, namun Ahya To tetap berkarya dalam keheningan. Hal selanjutnya yang orang-orang tahu, beliau mengeluarkan koleksi lukisan baru setiap 12 bulan.
Pagi hari saat waktu wawancara, Ardan memakan sarapannya sambil gugup, memikirkan apa yang akan dihadapinya hari itu. Ia hanya bisa bertanya-tanya orang seperti apa Ahya To sebenarnya. Tetapi pemikiran itu cepat-cepat ia singkirkan karena yang terpenting adalah ia harus memanfaatkan kemampuan jurnalisnya agar bisa mendapatkan banyak informasi penting tentang Ahya To.
Berdasarkan penuturan asisten Ahya To, beliau tidak ingin wawancara dalam bentuk video, beliau tidak terlalu percaya diri dengan penampilannya. Jadi, Ardan hanya perlu merekam suara beliau kemudian dipresentasikan dalam sebuah tulisan.
Ahya To juga berpesan bahwa sebisa mungkin Ardan datang sendiri. Alasannya, ia tidak terbiasa bertemu banyak orang. Itu membuatnya merasa terganggu.
Kemudian berangkatlah Ardan di hari wawancara menggunakan mobil pribadinya ke perumahan mewah di bukit kota itu. Cukup jauh dari pusat kota, tapi demi wawancara dengan Ahya To, Ardan tidak masalah akan hal itu. Untungnya waktu itu bukan hari libur, jadi perjalanan lancar dan Ardan sampai lebih cepat.
Kawasan tempat tinggal Ahya To sangat asri. Ada banyak pepohonan, udaranya sejuk, banyak perkebunan dan tidak terlalu ramai. Mungkin karena itulah banyak sekali rumah yang dijadikan vila oleh pemiliknya di sana. Tempat itu cocok untuk tempat istirahat bagi mereka yang lelah oleh hiruk pikuk kota besar.
Setelah Ardan pikir lagi, rumah milik Ahya To termasuk yang paling besar di antara yang lain. Gerbang utamanya terbuat dari kayu dan berukuran besar. Seorang satpam langsung membuka gerbang otomatis saat melihat mobil Ardan. Ardan terkesima melihat keindahan eksterior rumah Ahya To yang indah. Ia berpikir, mungkin itu salah satu kelebihan menjadi orang yang artistik, semua yang berhubungan dengan mereka pasti indah dan nilai estetikanya tinggi.
Ardan berjalan sambil melihat megahnya rumah Ahya To yang bernuansa cokelat dan putih. Rumahnya juga dihiasi banyak jendela dan tanaman-tanaman hijau. Halamannya luas sehingga butuh beberapa waktu bagi Ardan untuk sampai di pintu utama.
Ardan dengan hati-hati memencet bel di pintu utama dan tidak lama ada seorang perempuan yang merupakan asisten Ahya To. Ia berusia sekitar 35 tahunan dan terlihat sangat ramah. Ia tersenyum saat melihat Ardan dan langsung membuka pintu dengan lebar kemudian mengajak Ardan untuk masuk.
Bagian dalam rumah Ahya To juga sangat luas dan … kosong. Jika rumah mewah biasanya memiliki banyak furnitur mahal, dengan hiasan-hiasan dari emas, guci eksklusif dari Cina, atau bahkan lampu kristal yang menggantung di tengah ruangan, rumah itu tidak sama sekali.
Sofa dan beberapa meja diletakkan di tengah ruangan. Ada sebuah lampu hiasan di salah satu sisinya, tetapi selain itu, lantainya kosong. Temboknya yang berwarna putih juga kosong, tidak seperti bayangan Ardan tentang pelukis yang pasti banyak menggantung lukisan fenomenal dan mahal. Rumahnya sangat bersih dan beraroma seperti bunga lavender. Itu jadi menambah suasana lebih nyaman.
“Silakan duduk di sini. Saya akan memberi tahu Ahya To untuk bersiap-siap. Oh ya, nama saya Alika, bisa panggil saya kalau butuh sesuatu,” jelas Alika, wanita yang membukakan pintu tadi. Ardan mengangguk sambil tersenyum dan kembali memperhatikan rumah Ahya To.
Di lantai pertama, tidak ada ruangan selain dapur dan kamar mandi. Sementara di lantai kedua, terlihat ada dua pintu yang menurut Ardan adalah kamar milik Ahya To. Ardan masih belum mengerti kenapa rumahnya begitu kosong dan sepi.
Tidak ada suara apa-apa sejak tadi selain suara sepatu hak tinggi milik Alika yang sedang menaiki tangga. Ardan kira Ahya To punya keluarga yang besar, karena rumah itu pasti terlalu sepi untuk ditinggali sendiri. Tetapi melihat keadaan, sepertinya Ahya To memang tinggal sendiri. Ah, Ardan harus berhenti membuat spekulasi seperti itu.
Saat sedang jauh dalam pemikirannya, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Ia mengenakan baju rumahan dan rambutnya dicepol di belakang. “Mau minum apa, Mas?” tanyanya. Ardan memilih air putih saja dan wanita itu mengangguk, lalu berjalan ke dapur.
Beberapa menit kemudian, suara sepatu Alika terdengar lagi menuruni tangga. Ia tidak langsung menghampiri Ardan, tetapi menuju dapur, lalu seperti bicara sesuatu pada wanita yang menawarkan Ardan minum tadi. Setelah itu, barulah ia berjalan menuju Ardan.
“Ayo, Ahya To sudah siap di ruang kerjanya,” katanya lalu berjalan lagi menuju tangga. Ardan menaiki tangga kayu yang membuat banyak suara ketika seseorang berjalan di atasnya.
Sampailah Ardan dan Alika di depan salah satu pintu yang Ardan lihat dari bawah. Alika membuka pintu itu dan tersenyum sambil menunjukkan Ardan tanda bahwa ia sudah bisa masuk.
Dengan gugup, Ardan berjalan masuk. Lagi-lagi ia dibuat bingung, karena ruang kerja milik Ahya To hanya berisi 2 kursi dengan meja bundar kecil di antaranya. Ahya To duduk di salah satu kursi itu sambil menghadap jendela.
Ruangannya begitu besar jika hanya diisi dua kursi dan satu meja. Hiasan di dinding pun tidak ada, kecuali lampu ruangan yang sudah agak redup. Ahya To menoleh dan tersenyum kecil ke arah Ardan yang berjalan gugup sambil membungkuk sopan.
“Selamat siang, Pak,” sapa Ardan.
Ahya To menggeleng. “To saja. Panggil saya To.”
Ardan mengangguk, walaupun pasti canggung memanggil orang yang hampir dua kali umurnya hanya dengan nama. Ahya To menunjuk ke arah kursi di seberangnya, menyuruh Ardan untuk duduk.
Ardan duduk dan mengeluarkan ponselnya untuk merekam wawancara. Ia juga mengeluarkan buku catatan kecil, jaga-jaga jika ada poin yang harus ia catat. Sementara itu, wanita paruh baya tadi, masuk dan mengantar minum untuk Ardan. Ahya To juga minta dibawakan sesuatu, dari aromanya seperti teh hijau, juga sekotak biskuit cokelat untuk cemilan.
Setelah wanita itu pergi, barulah Ardan berbicara.
“Selamat siang, To. Saya Ardan, perwakilan dari perusahaan. Saya akan mewawancara Anda. Bisa kita mulai, To?” Ahya To mengangguk.
***
“Dan, saya duluan, ya? Sudah hampir jam 9.” Ardan menengok. Endi, salah satu teman sekantornya pamit kepada Ardan yang tinggal sendirian di kantor.
“Ya, Di. Silahkan.”
“Kamu gak mau pulang? Sudah terlalu malam, kerjaan mu selesaikan besok saja.”
Ardan menggeleng. “Tenggatnya justru besok, Di.”
“Ah, saya yakin Bos pasti ngerti. Kamu saja selesai wawancara hampir tengah malam, terlalu banyak yang belum selesai kalau tenggatnya besok.”
“Tak apa. Meski Bos menambah tenggatnya, saya ingin menyelesaikan ini secepatnya juga.”
“Ya, sudah. Saya duluan, ya. Kamu hati-hati.”
Ardan mengangguk dan berpesan pada Endi untuk menyampaikan ke satpam bahwa Ardan masih di ruangannya. Endi mengacungkan jempol lalu pergi.
Ardan berjalan ke arah loker di sudut ruangannya dan mengambil pengeras suara. Kemudian ia menyambungkan pengeras suara itu dengan ponselnya.
Lalu Ardan menyetel hasil rekaman wawancara dengan Ahya To dan menaikkan volumenya. Ardan menarik kursinya, mendekati jendela dan duduk menghadap jalanan kota yang masih ramai.
“Ah, saya-saya ingat. Perusahaanmu yang pertama-kali da-tang ke galeri saya. Maka-maka saya undang kamu karena-karena saya sudah-sudah janji.”
Suara gagap Ahya To terdengar dari pengeras suara.
“Janji apa, To?” Suara Ardan kemudian terdengar juga.
“Janji untuk-untuk wawancara pertama- dengan-dengan kalian saja.”
“Bisa saya tanya kenapa?”
“Saya-saya kira yang-yang pertama datang pas-pasti yang paling-paling tertarik.”
“Ah, tentu saja, To,” kata Ardan sambil tertawa sopan.
“Ar-dan? Apa kabarmu?”
“Saya baik, To. Bagaimana dengan Anda?”
“Baik. Te-tapi, saya agak se-sedih-karena-galeri-sa-ya -akan tutup.”
“Bukankah itu keputusan Anda sendiri?”
“Ya, betul. Teta-tetapi tidak se-semua keputu-san sendi-sendiri menye-nang-kan.”
“Ah, ya tentu saja. Apakah 18 tahun terakhir memuaskan untuk Anda?”
Ahya To mengangguk cepat. “Ya, ya. tentu.”
“Maaf sebelumnya, bisakah saya tanya kenapa To tidak pernah menerima wawancara sebelumnya?”
Ahya To menyeruput cangkir teh hijaunya sebelum bicara.
“Eh-eh. Saya-tidak su-suka bertemu ba- nyak o-orang. Lagi pula, ka-kamu lihat sendiri ke-keadaan sa-saya.”
Ardan hanya mengangguk saja.
“Kamu su-sudah makan?”
“Sudah, To. Tadi saya sudah sarapan di rumah.”
Ahya To melambaikan tangannya. “Pasti kamu su-sudah lapar lagi. Nan-ti saya su-suruh Ati bawa ma-kan, makanan.”
“Terima kasih, To.”
“Ya-ya-ya.”
“To, 18 tahun lalu, Anda membuat sebuah lukisan berjudul Kayu Manis dan Buah Persik. Kota ini masih belum paham akan makna mahakaryamu. Apakah bisa dijelaskan?”
Setelah mendengar itu, Ahya To menoleh ke arah jendela dan terdiam sesaat.
“To?” tanya Ardan setelah keheningan menyelimuti mereka selama beberapa menit.
“Ya-ya. Me-menurut saya, akan le-lebih baik jika saya ja-jawab setelah ma-makan siang. Ati, sep-seperti-sepertinya akan sege-ra da-datang,” katanya tanpa menoleh.
“Baiklah, To.”
Dan benar saja, Ati, yang sepertinya wanita paruh baya tadi, tak lama datang dengan sebuah troli. Ada terlalu banyak makanan jika hanya untuk dua orang. Dari ayam goreng, sebakul nasi, sayuran rebus, seteko air dan beberapa apel.
Pengeras suara berhenti. Rekaman suara berhenti. Ahya To dan Ardan makan siang tanpa bicara apa pun.
Setelah jeda itu, Ardan memutar lagi rekaman suara, di mana wawancara sebenarnya diabadikan.
“Jadi, apa itu Kayu Manis dan Buah Persik?”
“Sa-saya harus ta-tanya kamu dulu, a-apa itu?”
Ardan berpikir sebentar. “Jika saya lihat dari wujudnya, kayu manis adalah sebuah rempah, dan buah persik adalah buah. Namun saya yakin, makna sebenarnya bisa jadi bukan itu.”
“Mengapa?”
“Bukankah kayu manis dan buah persik tidak terlalu istimewa?”
Ahya To tertawa kecil. “Jika i-itu menu-menurutmu maka ka-kamu juga benar.”
“Maaf, To. Tapi saya yakin, jawaban saya jauh dari makna sebenarnya, bukan?”
Ahya To terdiam lagi. Kali ini tidak terlalu lama, lalu ia mendesah.
“Ah, akh-akhirnya saya ha-harus beritahu du-dunia juga ten-tentang dia.”
Ardan terdiam. Siapa yang Ahya To maksud? Namun Ardan tidak berani mengatakan apa pun, ia hanya menunggu Ahya To untuk melanjutkan kalimatnya.
“Ti-tiga puluh tahun la-lalu? Saya lihat di-dia di seberang ja-jalan sedang me-menunggu i-ibunya. Di-dia marah.”
“Maaf, To. Siapa yang Anda maksud?”
“Bu-bukan-bukankah tadi ka-kau tanya m-makna lukisanku?”
“Kayu Manis dan Buah Persik itu tentang seseorang?”
Ahya To tidak menjawab Ardan, namun tetap melanjutkan ceritanya.
“Saya ta-tanya sama tukang se-serabi, dia sering di-di sini? Kat-katanya ya, setiap so-sore. D-dia tunggu ib-ibunya.”
Ahya To menyeruput lagi teh hijaunya, yang mungkin sudah dingin sekarang.
“Ibunya suka ter-terlambat, mak-maka dia m-marah. Tapi k-katanya tidak dia tunju-tunjukan ke ib-ibunya.” Ahya To tersenyum sendu.
“S-saya tunggu d-dia kalau so-sore, d-dia selalu di-di sana. Kadang dia ba-bawa bekal, k-kadang tidak bawa apa-apa. D-dia suka pa-pakai kemeja sutra dan ce-celana kebesaran.”
Ahya To terdiam lagi cukup lama. Beliau menatap langit-langit sambil tersenyum kecil. Ardan juga hanya diam, ia terlalu masuk ke dalam cerita Ahya To.
“Se-sepertinya dia su-suka sekali sut-sutra. Dia pu-punya banyak war-warna. Dia ju-juga pakai s-sabuk, selalu.”
Tiba-tiba suara rintikan air terdengar dari jendela. Sedikit namun lama kelamaan deras. Ahya To masih belum bicara lagi, beliau justru menatap hujan di luar. Ardan tidak bisa apa-apa selain menunggu.
“W-waktu itu No-november, hujan ma-masih deras. Dia ti-tidak ada payung, sa-saya ada. Saya ka-kasihan lihat d-dia, tapi saya ta-takut. Jantung sa-saya berde-debar sek-sekali,” Ahya To tersenyum lebar dan pipinya membulat.
Ardan akhirnya berani bicara lagi. “Kenapa, To?”
“Be-beberapa minggu, sa-saya cuma berani li-lihat dari ja-jauh. Saya takut j-jika harus dar-dari dekat. Tapi sa-saya tetap lak-lakukan. Saya sebrangi ja-jalan, lalu ka-kasih pa-payungnya,”
“S-saya ingin bi-bicara tapi su-susah. Saya cu-cuma kasih s-saja. Dia ta-tanya, nanti sa-saya b-bagaimana. Saya bo-bodoh, sa-saya hanya di-diam saja. Tangan s-saya tetap kasih di-dia payungnya.” Ahya To berhenti lalu tertawa kecil.
“Dia j-juga bingung. D-dia lihat s-saya aneh. Tapi saya se-senang.”
“Mengapa, To?”
“Saya bisa li-lihat dia j-jelas.”
“Apa dia ambil payungmu, To?”
“Y-ya dia ambil. Saya balik la-lagi buru-buru. Saya ti-tidak bisa tidur malam i-itu. Pe-pertama dan terakhir ka-kali saya lihat di-dia begitu de-dekat.”
“Mengapa terakhir?”
“Dia su-sudah punya pa-payung.”
Ahya To melihat lagi ke luar. Hujan masih deras.
“To, saya belum mengerti hubungan cerita Anda dengan lukisan itu?”
“S-saya lihat d-dia jelas sore i-itu. Matanya c-cokelat, seperti k-kayu manis, bibir dan pi-pipinya merah s-seperti buah persik. Rambutnya hi-hitam panjang, dia p-pakai kalung e-emas.”
Ardan mengangguk mengerti.
“Lalu apa yang terjadi selanjutnya?”
“Saya te-tetap lihat dia dari j-jauh sa-sampai Juli.” Ahya To menarik nafas panjang.
“Hari i-itu dia c-cantik sekali. Dia p-pakai gaun me-merah selutut, r-rambutnya dia po-potong sebahu. Bibirnya t-tak lagi merah muda, warnanya s-sama dengan ga-gaunnya.”
Ahya To menelan ludah dan suaranya makin serak.
“S-saya kira itu wa-waktu saya akhirnya u-untuk bicara pa-padanya, maka s-saya jalan ke arahnya. T-tapi laki-laki lain je-jemput dia. Dia ci-ci-”
Ahya To terisak. Suaranya hampir hilang.
“D-dia ci-cium pi-pipi la-laki-laki itu.”
Kini Ahya To sudah menunduk dengan tangis di matanya. Hujan makin deras di luar sana.
“S-saya co-coba te-tap tu-tu-tunggu d-dia. S-sampai November da-datang lagi, d-dia tetap di-di sana, dengan la-laki-laki itu.” Ahya To semakin terisak.
Pengeras suara senyap. Ruangan Ardan sepi lagi. Ardan berhenti merekam saat tangis Ahya To semakin isak.
Ardan ingat, wajah Ahya To yang sudah usia semakin terlihat gelap karena tangisnya. Ardan keluar dari ruangan Ahya To agar beliau dapat privasi dan memanggil Alika.
“Saya tidak bermaksud, tetapi Ahya To sedang menangis di ruangannya.” kata Ardan sedikit khawatir. Alika terlihat khawatir dan langsung berlari ke ruangan Ahya To.
Ardan memutuskan untuk duduk di sofa ruang tengah Ahya To sambil mengusap-usap wajahnya. Ia tidak berpikir bahwa keadaan akan seperti ini. Tak lama Alika kembali dan mengatakan bahwa wawancara akan di lanjutkan hingga Ahya To ingin bicara lagi, saat ini beliau ingin waktu sendiri. Ardan hanya mengangguk dan menunggu.
Hujan sudah reda dan langit semakin gelap. Matahari sudah tenggelam dan Ardan masih duduk di ruang tengah rumah Ahya To. Ia tidak lihat siapa-siapa selain Ati yang mondar-mandir dari dapur ke arah taman lalu kembali lagi ke dapur. Alika juga tidak terlihat lagi.
Ardan bingung harus melakukan apa dan memutuskan untuk pamit pulang dengan Alika. Jadi, ia menghampiri Ati yang sedang merapihkan gelas dan bertanya keberadaan Alika. Ati bilang Alika sedang membaca buku di halaman.
Benar saja, Alika sedang duduk di bangku taman rumah itu dengan buku di tangannya. “Maaf, jika beliau masih belum ingin bicara, sebaiknya saya pamit saja dan lanjut wawancara esok hari.”
Alika menggeleng. “Tadi beliau berpesan, wawancara ini harus selesai hari ini. Kalau begitu biar saya cek keadaan beliau sekarang.” Kemudian Alika pergi dengan Ardan yang mengikutinya dari belakang.
Sampai di depan pintu ruangan Ahya To, Ardan berhenti mengikuti dan membiarkan Alika masuk. Tak lama, Alika keluar dan mengatakan bahwa Ardan sudah bisa masuk lagi.
Ardan duduk di kursi yang sama dan meletakkan ponselnya lagi di meja. Ahya To terlihat lebih baik meski matanya masih sendu.
“Maaf, To. Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda seperti itu.”
Ahya To menggeleng lagi. “Tidak i-ini salahku. Aku ti-tidak pernah berbicara be-begitu banyak se-seumur hidupku.”
“Baiklah, To. Kalau begitu bisa saya lanjutkan?” Ahya To mengangguk.
Ardan memutar lagi rekaman suara itu.
“Jadi, wanita di sebrang jalan itu adalah inspirasi Anda dalam membuat Kayu Manis dan Buah Persik?”
“Ya be-betul. Tapi tak ha-hanya itu, hampir se-semua lukisanku terins-inpirasi olehnya.”
“Jika saya boleh tanya, mengapa Anda tidak lukis wajahnya?”
“Cukup sa-saya dan laki-laki itu y-yang jatuh cinta, saya t-tidak kuat jika m-makin banyak yang meng-mengaguminya.”
“Apa Anda tetap melihatnya lagi setelah hari itu?”
“Ya. Namun di-dia berhenti da-datang pada De-sember.”
“Anda tidak pernah lihat dan dengar tentang dia lagi?”
“Tidak.”
“Baiklah, mungkin itu saja sudah cukup bagi saya. Terima kasih banyak.”
***
Ruangan Ardan senyap. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Ardan belum juga menemukan ide akan apa yang ia tulis di artikelnya. Jadi, Ardan memutuskan untuk datang ke galeri Ahya To, yang untungnya buka hingga tengah malam, jadi ia masih ada waktu.
Sesampainya, galeri sudah sepi, hanya ada beberapa orang yang sepertinya hanya butuh ketenangan dan duduk di kursi setiap sudut galeri.
Ardan berjalan dan melihat-lihat lukisan milik Ahya To. Lukisan Kayu Manis dan Buah Persik di pajang di tengah galeri. Lukisannya memang sederhana, namun setelah mengetahui maknanya, pandangan Ardan akan lukisan itu berubah.
Dan semakin berjalan, Ardan semakin mengerti makna lukisan-lukisan Ahya To. Ada lukisan tukang serabi, ulat sutra, halte, jalanan ramai, dan lukisan hujan. Ahya To melukis itu semua dengan perasaan yang dalam. Mungkin itulah kenapa, walaupun lukisan-lukisan Ahya To sederhana, tapi bisa dirasakan oleh yang melihatnya.
Seorang satpam memberi pengumuman bahwa galeri akan segera tutup, jadi Ardan berbalik dan memutuskan pulang. Karena terlalu lelah, Ardan langsung beristirahat setelah sampai.
Esok paginya di kantor, Ardan sedang mendengarkan lagi wawancaranya dengan Ahya To. Hingga Alika menelepon Ardan. Ardan terkejut, karena ia kira bisnis dengan Alika akan selesai jika wawancara itu sudah selesai.
“Halo?” kata Ardan.
Di seberang telepon, Alika sedang terisak, tanpa mengatakan apa-apa. “Halo?” kata Ardan lagi sambil mencoba meraih Alika.
“Ar-ardan? Maaf menganggu tapi saya ingin memberi tahu bahwa Ahya To sudah tidak ada.”
Apa? Apa Ardan tidak salah dengar?
“Maksudmu apa?” tanya Ardan untuk memastikan.
“Beliau sudah tiada, sejak tadi pagi. Bisakah kau datang kemari?”
“Ya, ya. Saya akan datang secepatnya.”
Maka dari itu, Ardan langsung mematikan telepon dan berlari menuju mobilnya. Meski Ahya To sejauh ini hanya narasumber untuknya, tetapi sungguh sedih mendengar berita itu.
Ardan menyetir kurang lebih 2 jam hingga tiba di rumah Ahya To. Apa pun yang Ardan bayangkan sama sekali tidak seperti kenyataannya. Rumah itu masih sama, sepi. Ardan kira kepergian Ahya To akan diantar banyak orang, termasuk penggemar atau keluarganya.
Ardan langsung melihat Alika yang sedang menangis sambil terduduk. Ia memakai baju serba hitam dan tisu ditangannya.
“Apakah saya telat?”
“Ya, beliau sudah dimakamkan setengah jam lalu.”
Ardan berdecak. “ Maaf saya terlambat, perjalanan cukup jauh dari kota.”
“Tidak apa, lagi pula akan lebih baik jika beliau cepat dimakamkan.”
“Alika, bisa ceritakan bagaimana kejadiannya?”
Alika mengangguk lalu berdiri. “Ayo, ikut saya.”
Ardan berjalan mengikuti Alika sampai di sebuah pintu namun bukan pintu ruang kerja Ahya To. Setelah dibuka ternyata itu kamar Ahya To.
“Ati mengantarkan sarapan dan obat untuk beliau, namun beliau tidak segera bangun. Ati menyentuh tangannya yang sudah dingin dan langsung lari memberi tahu saya. Beliau meninggal dalam tidurnya.”
Ardan mengangguk lalu menepuk pundak Alika dengan simpati. Mata Ardan menyapu kamar milik Ahya To dan ada satu yang menariknya. Lukisan seorang wanita. Wanita itu mengenakan kemeja sutra dan celana panjang. Rambutnya pajang dan rautnya marah. Wanita itu Kayu Manis dan Buah Persik.
“Alika, kamu tahu siapa perempuan itu?” tanya Ardan sambil menunjuk ke arah lukisan.
“Ya, dia si Kayu Manis dan Buah Persik.”
“Apa dia tidak punya nama?”
“Tentu punya, tapi beliau tidak pernah bertanya.”
“Beliau tidak tahu namanya?”
“Ya, beliau hanya lihat dia di seberang jalan dan tidak pernah bicara.”
“Mengapa?”
“Dia tidak pernah bilang padaku.”
Ardan hanya mengangguk dan kemudian Alika meninggalkan kamar itu diikuti Ardan. Mereka kembali duduk di sofa ruang tengah.
“Kamu mau minum apa?” tanya Alika kepada Ardan.
“Air putih saja tidak apa,” jawab Ardan lalu Alika berbalik dan mengambil segelas air putih.
“Di mana Ati?”
“Dia saya pulangkan untuk hari ini, dia terlihat sangat terpukul dengan kepergian To.”
“Alika, jika saya boleh tanya, mengapa rumah ini sepi sekali? Bukankah kepergian To pantas diantar banyak orang?”
Alika mendesah. “Aku juga berpikir begitu. Tapi siapa yang harus kuberi tahu? To tinggal sendiri, beliau tidak punya keluarga. Hanya Ati yang sudah bekerja dengan beliau sejak sepuluh tahun lalu. Aku hanya asistennya yang bekerja selama tujuh tahun terakhir.”
“Makanya aku memanggilmu untuk memberi tahu seluruh kota bahwa beliau sudah tiada,” lanjut Alika.
Ardan terkejut. “Beliau benar-benar sendiri?”
“Ya, dia tidak punya siapa-siapa. Dia pernah bilang padaku, hidupnya sudah berakhir sejak sore itu, saat dia lihat perempuan kayu manis dan buah persik itu dijemput oleh seorang laki-laki.”
Ardan terkesima. “Beliau berhenti hidup karena seorang wanita yang bahkan beliau tidak tahu namanya?”
“Ya, bisa jadi begitu. Namun bagaimana lagi? Kita tidak bisa mengatur bagaimana seseorang merasakan sesuatu.”
Ardan terdiam sesaat. “Lalu bagaimana dengan rumah ini?”
“Beliau ingin aku dan Ati menempatinya. Beliau juga bilang kalau bisa isi rumah ini dengan furnitur, karena tempat ini terlalu kosong.”
Ardan hanya mengangguk dan terdiam cukup lama. Karena tak ada alasan lagi untuk tinggal, Ardan pulang dengan hati yang masih berduka.
Ardan harus memberi tahu seluruh kota bahwa Ahya To sudah tiada. Entah bagaimana caranya, ia harus bisa. (*)
Carissa Fathina Maharani, biasa dipanggil Carissa. Lahir di Jakarta, 8 Desember 2004. Tinggal di Bekasi selama 10 tahun terakhir dan sekarang bersekolah di SMAN 2 Tambun Selatan kelas 3. Anak pertama dari tiga bersaudara. Menulis merupakan hobi dan subjek yang ingin dipelajari lebih jauh sampai bisa merilis buku.
Editor: Imas Hanifah N
Gambar: Pixabay
Mengirim/Menjadi penulis tetap di Loker Kata

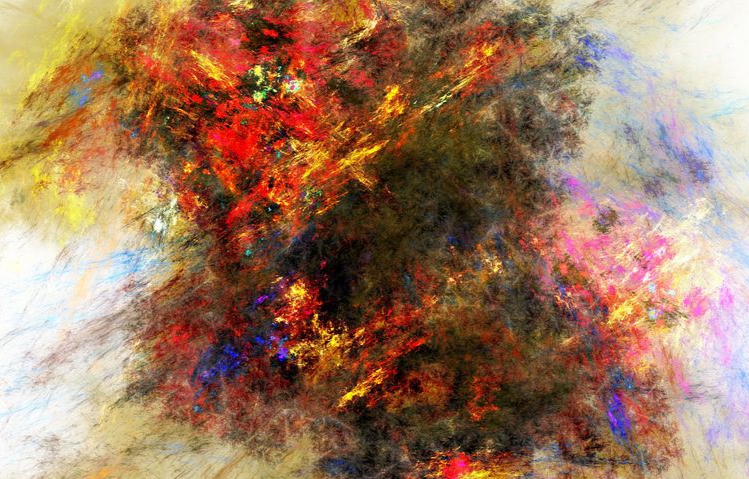



6 thoughts on “Kayu Manis dan Buah Persik”