Halusinasi
Oleh Rainy Venesiia
Satu senyum di wajah cerah menyambutku pagi ini. Walau aku yakin sebenarnya sambutan itu bukan untuk gadis berpenampilan buruk sepertiku, tapi nyatanya hatiku nyaman ketika melihat senyum itu.
Ah, ya, penampilan buruk. Itu yang dikatakan teman-temanku. Itu pun kalau mereka serius menganggapku teman, bukan olok-olokan atau merasa berteman ketika tak ada lagi orang lain di sekitar mereka. Aku tidak paham, penampilan buruk dan cantik itu seperti apa. Hanya saja, setiap kali mematut diri di cermin sambil membayangkan mereka, jelas sekali aku tampak berbeda. Rambut yang terikat sembarangan adalah perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan rambut mereka yang selalu tampak rapi. Kemeja panjang dan longgar dengan bagian tangan yang dilipat hingga pergelangan terlihat, sepatu olahraga tanpa kaos kaki, dilengkapi tas punggung tanpa aksesoris. Jauh dari kata fashionable , seperti halnya Arni.
“Kamu tuh jadul banget sih, Ka. Kaya remaja tahun 90-an,” celoteh sahabatku itu setiap kali melihatku siap pergi ke kampus. Kamarnya yang persis di sebelah kamarku, membuatnya leluasa mengintipku kapan saja. Aku hanya tertawa kecil sambil mengedikkan bahu.
“Kamu tuh manis, Ka. Coba deh, sedikit dandan dan itu kostum … aduuh!” protes Arni suatu kali ketika kami akan pergi bersama. Aku ingat saat itu kami menemui seorang kawannya yang seorang psikiater. Seorang perempuan yang sangat dewasa, ramah, sopan dan menyenangkan. Sejak hari itu Arni selalu mengajakku menemuinya. Katanya, Mbak Kekei sangat senang berbincang denganku dan aku tak bisa menolak.
Kembali pada senyum yang membuat sejuk mata dan hati nyaman itu. Sosoknya mendekat. Aku gemetar. Hatiku tak keruan. Meskipun semalam sudah menyiapkan mental untuk pertemuan pagi ini, tapi tetap saja aku salah tingkah dibuatnya. Kata-kata yang sudah kuhafalkan untuk menyapanya tertawan di kepala. Apalagi topik perbincangan yang mungkin dipilihnya dan menarik baginya mendadak raib. Dia makin mendekat dan hatiku berdebar-debar. Keringat sudah membasahi telapak tangan yang terkepal. Jantungku terlalu cepat memompa darah, lebih cepat dari kemarin sore saat dia menelepon.
Bagaimana tidak salah tingkah, jika kemarin dia menghubungiku untuk pertama kalinya selama satu semester saling berpapasan di koridor kampus, di depan papan pengumuman, di halaman musala dan di ruang tunggu dekan.
“Hai, Ka. Udah selesai?”
“Euh, masih ada satu matkul nanti jam dua.”
“Oh, lumayan masih lama.”
“Emang kamu mau ngomong apa, Nu?” Aku tak bisa menahan rasa penasaran lebih lama. Aku ingin menghentikan dag dig dug der di hatiku yang membuat pikiranku gagal fokus.
“Ngobrolnya di kantin yuk, biar nyaman.”
Apa? Oh, tidak. Bisa gempar seantero kampus jika banyak yang melihat kami berduaan makan di kantin. Berapa banyak gadis-gadis yang akan menatapku sinis dan penuh cemburu. Apalagi Arni, bisa satu minggu tertawa puas meledekku. Dia tahu kalau aku suka pada Ganu.
“Kenapa? Kok, bengong?”
Aku yakin saat ini wajahku pasti tampak merah seiring panas yang menjalar. Dia pasti melihatnya dan itu membuatku gugup.
“Euh, emang gak bisa langsung aja?”
“Bisa sih, tapi biar nyaman saja. Gak enak kan, ngobrol sambil berdiri?”
Aku tidak ingin berbaik sangka dan sengaja menyuruh hatiku berbunga-bunga, tapi pikiranku sudah mengembara liar tak terkendali. Pertanyaan apakah dia suka padaku, benar-benar sangat mengganggu konsentrasi. Segera aku memerintahkan pikiranku agar tak berharap. Siapalah Tika. Bukan siapa-siapa dan tak ada apa-apanya dibanding para gadis di sini. Ini dunia nyata bukan kisah fiksi yang logikanya bisa diatur. Apalagi macam sinetron yang jarang kutonton. Aku mengembuskan napas, lalu tersenyum kecut menyadari hal itu.
“Kenapa?”
“Euh, tidak. Ya udahlah, hayu kita makan tapi kamu yang traktir, ya.”
Dia tertawa sambil menjajari langkahku. Aku menahan diri untuk tidak memukul pangkal lengannya, seperti yang sering kulakukan pada sahabatku, dulu. Tiba-tiba hatiku dipenuhi awan mendung teringat seseorang. Seseorang yang pernah sangat kucintai dan aku mempercayai cintanya padaku.
Aku tertegun melihat Ganu menyisihkan bawang goreng di tepi piring.
“Kenapa tak bilang saja gak usah pake bawang kalau gak suka. Kan, sayang dibuang.”
Ganu terkekeh.
“Kau tak berubah.”
“What?”
Aku mengamati wajahnya dengan saksama. Rambut, alis, hidung, bibir, dan tangannya. Cukup lama aku termenung, berusaha mengingat barangkali sosok di depanku ini adalah teman lama atau salah seorang kenalan di suatu perjalanan. Namun, nihil. Tak ada kenangan atau catatan tentang sosok di depanku itu. Semuanya asing kecuali dia adalah makhluk ganteng penghuni kampusku yang belum pernah saling menyapa sekali pun sebelum ini.
“Kau tidak ingat?”
Aku menggeleng.
“Baguslah karena memang kita tak pernah punya masa lalu bersama.” Dia tertawa, tampak nikmat sekali.
“Tapi kau pasti ingat Has.”
Aku meletakkan sendok yang baru saja kuangkat hendak bersuap. Baru saja nama itu kuusir karena aku tak ingin menangis di sini, di depan laki-laki yang aku suka, apa lagi di tempat ramai seperti kantin ini. Kantin yang menjadi tempat tujuan para mahasiswa bahkan dari fakultas lain karena harganya yang manis.
“Kau siapa?” Aku menatapnya tajam. “Apa hubunganmu dengan Has?”
“Aku?” Ganu membalas tatapanku. “Tentu saja aku reinkarnasinya.”
“Tidak lucu!”
Aku berdiri dan meninggalkan piring yang masih setengahnya berisi ketoprak dengan bawang goreng melimpah dan kerupuk mie kesukaanku. Terdengar suara Ganu memanggilku dan sepertinya ia mengejarku. Aku tak ingin menoleh, malah bergegas menuju musala yang berada persis di belakang kantin.
“Aku minta maaf, Ka.”
Suara Ganu sangat jelas terdengar ketika aku hendak membuka sepatu. Aku berbalik dan melihatnya berdiri tegak menatapku. Tangan kanannya ia letakkan di dadanya. Dari balik air mata yang tak bisa kutahan, aku bisa melihat kesungguhan di wajahnya. Aku mengangguk dan dia tersenyum. Lantas, dia mengeluarkan sebuah buku dari kantung ransel warna hijau tua, sekilas mirip ransel yang sering kulihat dipakai tentara.
“Ini milik Has, untukmu.”
Aku menatapnya tak mengerti. Dia mengangguk dan menceritakan bagaimana buku diary milik Has berada padanya. Singkat. Ya, dia menceritakan terlalu singkat, hanya dalam beberapa kalimat saja, lalu dia pergi meninggalkanku terpaku, berusaha mencerna apa yang dia katakan. Andai Arni tak menggandeng dan menyeretku pulang, entah akan berapa lama lagi aku berdiri bengong di depan musala.
Semalaman aku tak bisa tidur memikirkan kata-kata Ganu. Benarkah mereka saudara kembar tak identik. Benarkah Has sangat mencintaiku hingga akhir hidupnya. Jika benar, betapa aku akan menyesal seumur hidupku telah mengusirnya dengan kata-kata yang sangat kasar. Cemburu buta. Benarkah aku telah gelap mata karena cemburu, padahal aku tak pernah menyelidiki kebenaran hubungannya dengan adikku. Aku terlalu sombong, kata Ibu. Terlalu angkuh untuk mendengar penjelasan dari dua orang yang sangat kucintai, Has dan adikku. Bahkan, aku tak ingin melihat keduanya dan Ibu tak mampu mencegahku untuk pergi dari rumah.
Kecelakaan maut itu, kecelakaan yang telah merenggut nyawa Has dan adikku, katanya terjadi saat mereka mencariku. Namun, aku tak ingin mempercayai cerita yang Ibu sampaikan dengan isak tangis. Aku hanya percaya pada apa yang kulihat dan aku telah melihat mereka saling memeluk di tepi kolam di taman kota. Sama dengan malam ini, aku tak ingin mempercayai apa yang dikatakan Ganu maupun semua rangkaian kalimat yang tertulis di buku yang baru saja kulempar ke kasur.
Akan tetapi, aku tidak tahu bagaimana Ganu menghilang setelah hari kemarin. Anehnya, tak ada gosip tentang menghilangnya sosok ganteng yang jadi rebutan para gadis dan gadis-gadis yang selama ini tampak berusaha keras mencari perhatian Ganu pun, sepertinya tak ada yang membicarakan idolanya. Benar-benar tak ada pemberitaan tentang Ganu, seolah-olah sosoknya tak pernah ada. Begitu pun dengan Arni, dia malah mengambil buku diary milik Has dan berkata bahwa seharusnya aku tak lagi membacanya. Aku tercekat.
“Aku baru membacanya. Kemarin Ganu memberikannya padaku.”
Arni menggeleng dan tersenyum. Tatapannya seakan-akan penuh rasa kasihan. Dia menepuk pundakku dengan lembut dan berkata bahwa besok adalah jadwalku bertemu Mbak Kekei.(*)
Bandung, 25 Maret 2021
Rainy Venesiia adalah seorang wanita yang senang menulis. Sebagian sudah diterbitkan dalam antologi bersama. Beberapa cerpennya bisa dinikmati di website loker kata.
Editor : Freky Mudjiono

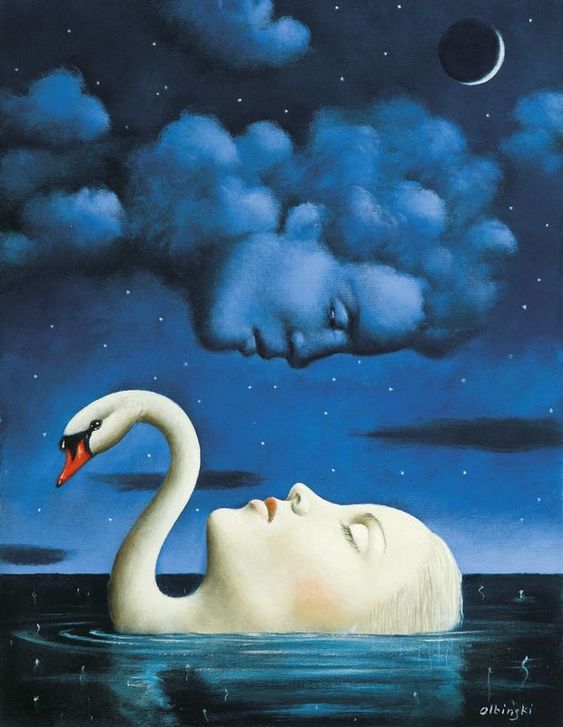



13 thoughts on “Halusinasi”