Di Tanah Lada; Kepolosan Seorang Bocah dalam Memandang Dunia
Oleh: Ika Mulyani
Terbaik ke-6 Event Review Buku Loker Kata
“Kecuali di Australia. Tempat aneh itu tidak pernah setuju soal perhitungan cuaca. Mama yang memberitahuku. Katanya, kalau seluruh dunia sedang kedinginan, Australia akan kepanasan.”
“Bagian dalam rumahku seperti Australia. Di luar adalah seluruh dunia yang lain. Di luar panas.”
“Tapi di dalam sini terasa dingin.”
“Bukan karena AC, tapi karena rasanya memang dingin. Bagian dalam rumah selalu gelap.”
“Seperti ada hantu yang menggerayangi seluruh bagian rumahku.”
“Hanya saja, di sini, hantunya hidup. Hidup, berbadan besar, dan sangat menakutkan.”
“Nama hantunya Papa.”
Novel Di Tanah Lada adalah karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie setebal 245 halaman. Ternyata nama penulis bukan nama pena seperti perkiraan saya. Ia terlahir sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, yang keempatnya bernama depan Ziggy, dengan nama belakang yang juga panjang. Ia berspekulasi bahwa orangtua mereka terinspirasi oleh album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider from Mars karya David Bowie.
Ziggy Zezsya seorang sarjana hukum yang telah menulis puluhan novel—kebanyakan bergenre fantasi. “Di Tanah Lada” sendiri merupakan novel realis, dan berhasil meraih juara kedua dalam Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Dua tahun kemudian, karyanya yang lain, “Semua Ikan di Langit”, menjadi pemenang dalam sayembara yang sama. Pada Agustus 2015, Gramedia menerbitkan “Di Tanah Lada” dan enam tahun kemudian buku itu dicetak ulang dengan cover baru tanpa ada revisi dalam isinya.
Novel ini mengisahkan tentang seorang bocah perempuan bernama Salva. Sejak Kakek Kia (ayah papanya) meninggal, jalan hidup gadis kecil itu benar-benar berubah. Warisan uang yang banyak dari sang kakek malah membuat hidup mereka jadi makin berantakan, karena ulah “Hantu Papa”.
Tanah Lada sendiri adalah kampung halaman mama Salva. Gadis kecil itu sayang dan sangat peduli pada mamanya. Mungkin karena melihat bahwa ketika di sana sang mama selalu tampak bahagia, tidak muram seperti saat di rumah, maka ia menganggap tempat itu istimewa. Tempat itulah yang dituju oleh Salva dalam perjalanan ceritanya.
Narasi cerita dituturkan dengan mengambil sudut pandang Salva yang masih berusia enam tahun. Teknik ini benar-benar berhasil dan menjadi poin plus cerita. Saya tersenyum-senyum setiap kali membaca kepolosan Salva dalam menanggapi apa saja.
Sebuah kamus selalu menemani ke mana pun Salva pergi. Ia sangat hafal tulisan yang tertera di halaman depan kamus itu: “Budi bahasa baik membentuk manusia bersahaja. Selamat ulang tahun yang ketiga, Ava. Dari Kakek Kia.” Salva akan mencari arti semua kata yang tidak dipahaminya di dalam kamus itu, atau dengan mengingat penjelasan sang kakek tentang kata yang dimaksud. Cara Salva menyimpulkan makna sebuah kata atau frasa seringkali jadi menggelikan. Misalnya pada saat Salva ingin mencari tahu tentang arti kasino.
‘Menurut kamus, kasino berarti ‘tempat menyelenggarakan perjudian secara legal.’
Karena merasa asing dengan kata perjudian dan legal, Salva mencari lagi di dalam kamus.
‘Aku agak (sangat) bingung karena definisinya panjang sekali. … Tapi akhirnya aku tidak benar-benar tahu arti kata ‘kasino’.
‘Petunjuk lain tentang arti ‘kasino’ adalah ucapan Kakek Kia ketika dia mengobrol dengan Mama. Mereka sedang membicarakan tiga orang pemilik warung kopi bernama Dono, Kasino, dan Indro. Nama ‘Dono’ mirip dengan nama Papa dan nama temanku yang jahat (mereka sama-sama bernama Doni). Nama ‘Kasino’ mirip dengan ‘kasino’ yang disukai Papa. Yang disukai Papa biasanya adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi, kusimpulkan, Indro adalah satu-satunya orang yang baik di warung kopi itu.’
‘Ketika Papa pergi ke ‘kasino’, berarti Papa mengunjungi pemilik warung kopi untuk bermain bersamanya.’
Masih banyak hal-hal semacam itu bertebaran di sepanjang cerita dan kadang sampai membuat saya tergelak; narasi yang konyol, kekanakan, naif, tetapi bisa jadi benar, satire. Namun, ketika saya membaca buku ini untuk kedua kalinya, saya merasa sulit untuk tersenyum. Saya malah merasa miris. Mungkin karena saya sudah mengetahui keseluruhan ceritanya.
‘Tidak ada Papa yang baik di dunia ini.’
Dan ini ucapan Salva kepada sahabatnya—seorang bocah laki-laki sepuluh tahun bernama P yang selalu membawa gitar kecil di punggungnya: “Tapi kalau semua orang yang dalam hidupnya ada orang jahatnya itu hidupnya nggak normal, berarti semua orang hidupnya nggak normal, dong? Kan, semua Papa jahat. Semua orang, kan, punya Papa.”
Sementara itu, di halaman akhir novel, penulis menyertakan sebuah “Catatan Cetakan Kedua” yang di dalamnya terdapat kalimat: “… sebagai penulis, saya punya interpretasi yang tidak menyimpulkan buku ini dengan kelam seperti yang diyakini banyak pembaca.”
Sejujurnya, pada pembacaan pertama, saya menilai cerita dalam buku ini memang kelam. Dalam pembacaan kedua, saya mencoba memahami maksud catatan itu. Saya mencoba membaca dengan lebih saksama, bagaimana Salva berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya, terutama dengan P.
Akhirnya saya menyimpulkan, bahwa penulis mencoba menggambarkan dunia anak-anak sebagai dunia yang dipenuhi aura kesenangan. Mata anak-anak biasanya selalu berbinar penuh semangat dan mereka selalu berhasil melihat sisi positif dari berbagai kejadian yang dihadapi, bahkan dari hal yang bisa dianggap paling buruk oleh seorang dewasa.
‘… tapi kurasa kami akan tinggal di rusun itu. Dan, meskipun aku tidak keberatan, sepertinya Mama tidak senang. Soalnya Mama menjerit-jerit.’
Tentu saja anak-anak pun bisa marah, sedih, atau kecewa, tetapi mereka tak pernah berlama-lama larut dalam emosi.
‘… Karena aku masih marah, aku pukul lagi dia … sampai aku capek dan lupa kenapa aku memukulnya.’
Sejatinya, anak-anak jauh lebih “kuat” dari orang dewasa, mungkin karena itu mereka selalu terlihat bahagia.
Saya mencoba membandingkan cara Salva berpikir dengan bagaimana Harry Potter menjalani sebelas tahun pertama hidupnya dalam “penindasan” keluarga Dursley, bibinya sendiri.
‘… Harry turun dari tempat tidur dan mencari-cari kaus kaki. Ditemukannya sepasang di bawah tempat tidur, dan setelah menarik labah-labah dari salah satu di antaranya, dipakainya kaus kaki itu. Harry sudah terbiasa dengan labah-labah, karena lemari di bawah tangga penuh labah-labah, dan di situlah dia tidur.’
Harry hampir tidak pernah mengeluh, selalu terlihat santai dan mampu mengubah persepsi tentang apa pun yang tampak menyedihkan menjadi hal yang konyol di dalam pikirannya. Ketika sepupunya mendapatkan puluhan hadiah di setiap hari ulang tahunnya, Harry “woles” saja, walaupun ulang tahunnya sendiri selalu terlupakan. Ia bahkan bisa menemukan sisi lucu yang diam-diam ia tertawakan—meski hanya di dalam hati.
Sepositif itulah agaknya seorang anak memandang dunia, sementara kita orang dewasa hampir selalu “lebay”. Ini sejalan dengan kalimat terakhir dalam catatan penulis: “… terus merayakan harapan utama yang menggagas kelahirannya (buku ini): Semoga semua anak hidup bahagia.”
Ciawi, 27 Mei 2024
Ika Mulyani, emak-emak Lokit yang masih sedang belajar untuk menjadi pembaca dan penulis yang baik.
—
Komentar juri, Imas Hanifah:
Di Tanah Lada, karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie, sudah lama sekali saya ingin membaca karya ini. Namun, saya masih ragu-ragu. Beruntungnya, saat saya membaca review Ika tentang novel ini, saya memutuskan untuk segera memasukkan novel ini ke dalam wishlist buku yang akan saya beli.
Beberapa kutipan yang ditampilkan di dalam review Ika bisa dibilang semakin menambah rasa penasaran saya. Apalagi ketika Ika menambahkan kutipan dari Harry Potter untuk meyakinkan pembaca mengenai seperti apa sosok Salva di dalam novel ini. Cukup unik dan itu berhasil.
Event review buku ini diselenggarakan di grup facebook Komunitas Cerpenis Loker Kata.

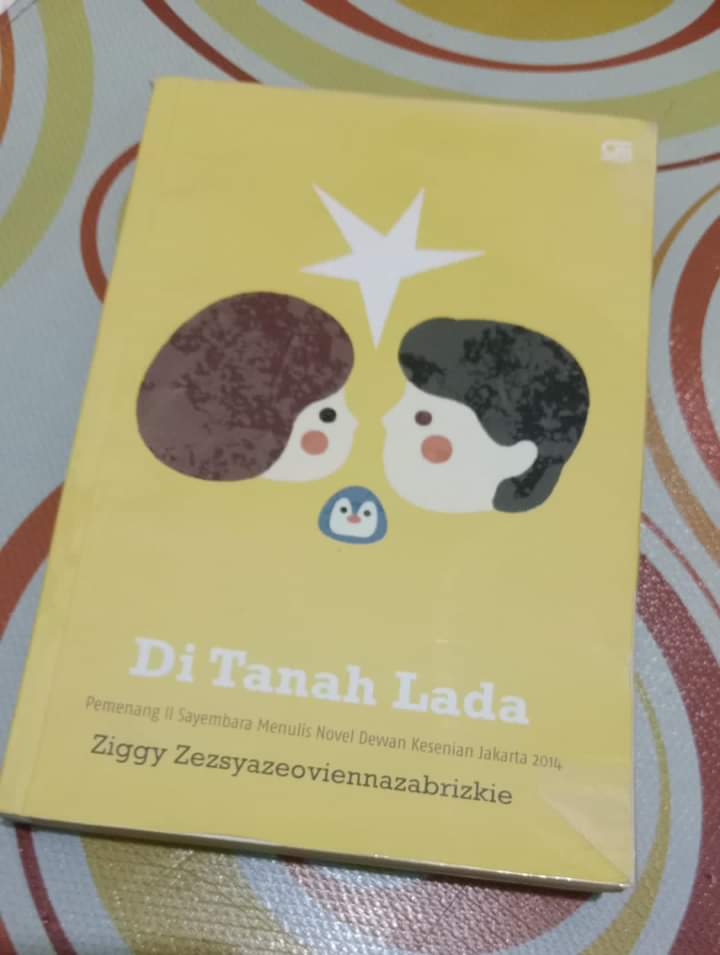



7 thoughts on “Di Tanah Lada; Kepolosan dalam Memandang Dunia”