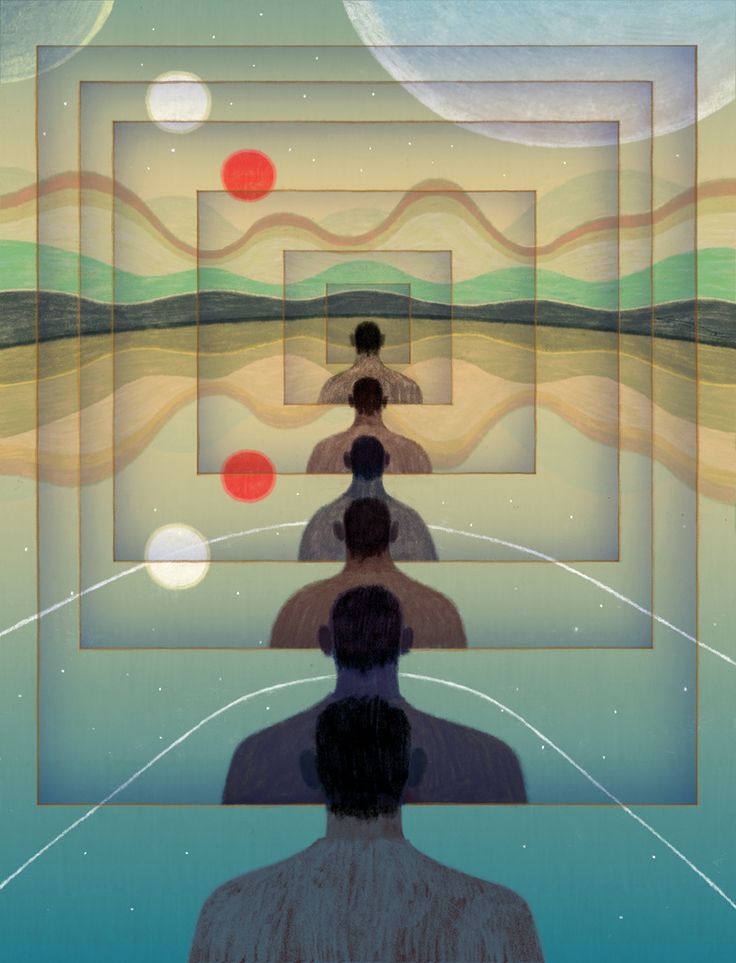Tantangan Loker Kata 21
Naskah Terbaik ke-5
Bukan Saya?
Oleh : Erien
Ada yang aneh dengan lampu jalan antik di pertigaan ABC Straat. Sorotnya berwarna jingga hampir sebulan ini. Dan itu berbeda dari lampu lain yang warna cahayanya putih. Saya menyadarinya ketika pulang dari menjaga toko jam kuno di ujung jalan ini.
Apa pemerintah kota kehabisan lampu putih? Apa ada yang iseng menggantinya? Atau malah lampu itu mulai rusak?
Sepertinya, hanya saya yang memperhatikan lampu itu. Tidak ada orang lain yang mau membahasnya. Termasuk penjaga toko di sekitar lampu. Sorot lampu jalan tentu kalah dibanding perut lapar, kejaran cicilan dan pinjol, ataupun godaan judol.
Saya pun, jika saja tidak rutin membuang sampah di tong yang terletak tepat di bawah tabung sinarnya, tidak akan peduli. Hanya karena cahayanya yang sekarang sedikit mengganggu, saya jadi mulai memperhatikan. Cahaya jingga itu membuat tong sampah jadi tampak lebih muram, lebih gelap, lebih berantakan, dan lebih … bau?
Mungkinkah spektrum cahaya lampu yang berwarna jingga membuat bakteri berkembang biak lebih cepat? Saya tidak tahu. Saya tidak sepintar itu. Bahkan, saya tidak tahu arti kata spektrum dan dari mana pikiran itu datang.
“Oranye? Lampu di pertigaan sana?” Reaksi pemilik toko, namanya Koh Wan, tempat saya bekerja adalah yang paling menarik saat saya menceritakan lampu itu. Apalagi kalimat berikutnya. “Tong sampahnya masih ada?” Dia menatap saya dengan alis terangkat.
Apa hubungannya?
“Sudah, jangan dipikirin. Biarkan saja seperti itu. Jangan sekali-kali kau pindah tong itu.”
Cahaya lampu berwarna jingga, tong sampah, reaksi Koh Wan, dan “jangan dipindahkan”. Bagaimana saya yang kepo ini bisa menurut?
Malam itu, saya pulang agak larut. Toko memang tutup di jam seperti biasa. Namun, saya harus mengambil obat untuk kakak perempuan saya, Kak Ira. Sebenarnya, saya bekerja di toko jam itu untuk menggantikannya. Sebabnya adalah dia tiba-tiba tidak lagi bicara. Lalu, dia mulai menangis, sebulan kemudian tambahlah ketawa terlalu sering. Rambut panjangnya terpaksa saya gunting pendek karena dia tidak mampu mencuci sendiri. Tubuhnya sangat kurus. Semua tidak saya tahu penyebabnya. Dan kini obat harus dikonsumsinya tiap hari. Saya tidak memberi tahu dia bahwa sayalah yang menggantikan posisinya di toko jam kuno itu. Saya takut melukai hatinya.
Sampai di lampu jalan bercahaya jingga, saya berhenti. Tong sampah masih ada tepat di bawah cahayanya. Saya menggesernya dengan pelan. Kemudian, setelah berdiri tepat di tengah sorotan lampu, saya mendongak.
Silau.
Saya memejamkan mata lalu mundur sedikit dan menabrak tong sampah. Untungnya tidak sampai terjatuh, baik saya maupun tong sampahnya.
Saat menoleh ke belakang untuk mengecek tong, sudut mata saya menangkap sosok perempuan.
Lho? Itu Kak Ira. Dia berjalan terseok-seok sambil memeluk tasnya. Bajunya … kenapa dia memakai seragam batik toko jam? Apa dia kangen dengan tempatnya bekerja? Dari mana dia? Arah langkahnya seperti hendak menuju toko. Bukankah ini sudah terlalu malam untuk ke sana?
Saya berteriak memanggil namanya. Tapi Kak Ira sepertinya tidak mendengar. Kak Ira yang saya lihat seperti Kak Ira yang dulu. Bukan yang sakit seperti sekarang. Badannya berisi dengan rambut terkuncir rapi. Bagaimana bisa rambutnya tiba-tiba panjang seperti itu? Sebab merasa aneh, saya pun mengikutinya.
Kak Ira masuk ke toko. Sewaktu saya hendak ikut masuk, terlihat dari kaca, Kak Ira dan Koh Wan seperti sedang berdebat, bertengkar, atau entah apa. Kak Ira menunjuk perut dan menunjuk Koh Wan. Laki-laki itu menggeleng-geleng sambil mengacungkan telunjuk ke arah pintu. Kak Ira menangis.
Tentu saja saya merasa harus masuk untuk membela Kak Ira, membantu, atau apa saja. Tapi, saat saya membuka pintu toko dan lonceng di atas pintu toko berbunyi, tidak ada Kak Ira di dalam. Hanya Koh Wan yang sedang membereskan catatan hari ini.
“Ngapain balik lagi? Ada yang ketinggalan?” Pertanyaan Koh Wan membuat saya kebingungan.
“Mana Kak Ira, Koh?”
“Ira? Mana aku tahu. Bukannya dia ada di rumah?”
Saya pun keluar sambil bergegas menelepon tetangga untuk memastikan bahwa Kak Ira masih di rumah. Dan iya, Kak Ira sedang duduk di sofa seperti biasa, menunggu saya pulang.
Kok, bisa?
Kembali melewati pertigaan lampu bercahaya jingga, saya melihat tong sampah sudah ada di tempatnya. Tong hitam itu seperti penyanyi yang sedang konser di panggung dan disorot cahaya lampu.
Saya menoleh ke belakang karena merasa ada yang mengikuti. Seseorang berjalan santai menuju arah saya sambil menengok ke lampu jalan itu. Dia berhenti. Saya terbengong.
Laki-laki itu saya. Dia itu saya! Saya yang tadi beli obat. Buktinya, kresek putih itu masih saya pegang.
Dia, eh, saya yang itu …. Duh, bagaimana cara menjelaskannya. Diri saya yang itu berjalan menuju tong sampah lalu menggeser tong itu. Kemudian, berdiri di bawah cahaya lampu.
Sebentar. Bukankah ini sama seperti apa yang saya lakukan sebelumnya?
Saya yang itu kesilauan dan mundur menabrak tong sampah. Saya ikut kesilauan hingga menutupi mata dengan lengan. Saat lengan saya turunkan, diri saya yang lain sudah menghilang.
Mungkinkah saya ini mengantuk? Atau terlalu lelah menggosok jam-jam kuno itu sehingga saya berhalusinasi?
Saya memutuskan untuk pulang saja. Untung bus terakhir masih sempat terkejar. Banyak sekali pertanyaan dan saya tidak tahu jawabannya. Sekarang, saya hanya ingin melihat Kak Ira dan menemukannya dalam keadaan baik-baik saja.
Tepat di pintu rumah, saya mendengar Kak Ira terisak-isak. Dia berbicara seperti sedang menelepon seseorang. Urunglah niat saya untuk langsung masuk rumah.
“Aku sudah nurut, Koh. Sudah aku gugurin, Koh. Kenapa sekarang malah Koh Wan tidak mau sama aku?”
Otak saya menangkap omongan Kak Ira dan menyimpulkan satu cerita. Seketika, saya merasa ingin mema tahkan leher Koh Wan. Ternyata, laki-laki beristri beranak itulah penyebab sakit Kak Ira.
Saya mengintip dari jendela yang kordennya tersingkap di ujung. Tampak Kak Ira duduk di sofa sambil menangis.
Itu Kak Ira yang lama! Badannya berisi.
Ketika sedang memperhatikan Kak Ira, saya terkejut dengan suara pintu terbuka. Hanya lengan dan sepatu yang terlihat. Kak Ira berhenti menangis. Saya kembali mengintip.
Kak Ira tersenyum menyambut orang yang datang. Saya hanya melihat punggungnya, tapi mengenali jaket yang dipakai.
Itu saya. Saya yang lain. Dan adegan ini saya ingat. Wajah Kak Ira sembab tapi saya tidak berani bertanya. Saya yang baru pulang dari rumah teman, hanya mencium tangan dan sebisa mungkin menurut padanya. Tapi, bagaimana bisa saya melihat semua ini?
Sejenak saya bingung harus bagaimana. Tapi, sepertinya saya harus masuk untuk memastikan semua. Dan ketika saya membuka pintu, Kak Ira yang kurus dan bermata kosong sedang duduk di sofa seperti biasa, menunggu saya pulang kerja. Tidak ada saya yang berjaket.
Ini tidak beres.
Saya meletakkan obat dan memutuskan naik ojek kembali ke toko. Atau ke lampu jalan bersinar jingga, tempat semua berawal.
Tepat di depan toko saya berhenti dan turun dari ojek. Sedetik setelah beres dengan bayaran ojek, saya mematung melihat adegan di toko pintu. Ada saya yang membuka pintu. Itu saya yang tadi. Saya yang melihat Kak Ira berdebat dengan Koh Wan. Saya yang masuk lalu mendapati Koh Wan sedang membereskan catatan. Saya yang memastikan Kak Ira masih di rumah.
Di trotoar dekat lampu jalan itu, terlihat Kak Ira berjalan terseok-seok.
Saya menelan ludah. Rasanya dada ini sangat sesak. Bernapas pun terasa susah. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Di mana saya? Kenapa banyak sekali saya, Kak Ira, dan Koh Wan?
Dengan punggung dan dahi yang banjir keringat dingin, saya mendekat ke lampu bersorot jingga itu. Tong sampahnya kali ini belum kembali ada di bawah sorot lampu. Tong itu bergeser seperti sebelumnya.
Seseorang menabrak saya dari belakang. Dengan terhuyung-huyung saya menahan agar tidak sampai jatuh. Orang itu mendekat ke tong sampah, lalu menggesernya hingga ke tempat semula: tepat di bawah sorot lampu.
Itu Koh Wan!
Dia melirik ke arah saya. “Kau sembrono. Sudah kuperingatkan. Sekarang rasakan sendiri akibatnya.”
Badan saya seketika tegak lalu mendekat kepada Koh Wan. “Apa ini, Koh?”
Tidak ada jawaban. Dia malah sibuk mengatur tong agar tepat ada di tengah.
“Bagaimana mengembalikannya, Koh?”
Laki-laki itu menoleh pelan. “Kau pikir aku tahu? Kau pikir aku adalah Koh Wan yang kau temui? Bagaimana jika aku adalah Koh Wan yang lain?”
Saya terdiam dan mulai ketakutan. “Gimana cara baliknya, Koh?”
Koh Wan menghela napas. “Entah. Mungkin kau bisa coba caraku. Aku membunuh aku yang lain agar tersisa hanya aku.”
Saya mundur lalu menangis.[*]
Kotabaru, 5 Agustus 2025
Erien, berjuang menjadi anak, istri, dan ibu yang baik.
Komentar Juri, Halimah Banani:
Sejak pertama baca naskah ini, saya langsung terpukau. Idenya menarik dan narasinya baik. Erien berhasil menyajikan ide yang berat ini dengan cara yang mudah dipahami. Sayangnya, konflik di dalamnya cukup banyak sehingga membuat cerpen ini jadi terasa begitu rumit dan membuat fokus ceritanya pecah.