Aku dan Ruangan yang Dahulu Kosong
Oleh: Retno Ka
Ruangan ini benar-benar kosong saat aku pertama kali datang. Lantai marmer dan kaca jendelanya masih sangat kinclong. Dinding berwarna mint-nya pun masih menguarkan aroma cat yang belum lama kering. Bersama dengan puluhan hadiah lain yang masih terbungkus rapi, aku diletakkan di salah satu sudut ruangan. Kami—aku dan hadiah-hadiah lain—berdesakan selama tiga hari tiga malam dengan lampu yang tidak dinyalakan. Sementara Nauren dan Fran, tampaknya pergi ke suatu tempat untuk berbulan madu. Aku tidak masalah, baik siang atau malam, karena selain posisiku paling atas, yang membungkusku adalah kaca mika bening dengan lilitan seutas pita kuning; aku tak merasa pengap sebagaimana mereka yang berada di bawahku. Salah satu dari mereka terus saja mengeluh karena tak betah terus ditindih. Tentu saja aku tak menanggapi, meski di saat-saat tertentu aku akan sangat terganggu.
Sekembali Nauren dan Fran ke ruangan ini, mereka ternyata tak langsung menyentuh kami. Mereka mempersilakan tiga orang lelaki berseragam biru masuk ke ruangan ini untuk membawakan ranjang berukuran nomor satu. Ranjang itu mengaku didatangkan langsung dari Jepara. Entahlah, daerah apa itu, aku belum pernah dengar sebelumnya.
Seusai mengatur letak ranjang dan tiga orang lelaki itu pergi, Nauren akhirnya mendatangi kami. Dipindahlah aku ke sisinya, dan ia mulai membuka hadiah-hadiah itu dari yang bentuknya paling kecil. Ada piyama panjang dari Eveny, selembar gorden coklat dari Helena, dua mug porselen dari Beth. Di dalam setiap hadiah ada sebuah kartu ucapan selamat untuknya dan Fran, dan ia tampak berbinar-binar setiap kali membaca kartu itu satu-satu. Binar wajah itu bersamaan dengan lenguh lega dari para hadiah yang berhasil dibuka. Mereka bersorak dan saling menyapa, dan akhirnya aku pun tahu suara siapa yang paling berisik saat kami masih saling bertumpukan. Dia Gorden.
“Hai, Kaktus, kau manis sekali,” sapa Gorden.
“Terima kasih,” jawabku singkat. Aku tak berniat memperpanjang percakapan dengannya.
Sementara Nauren asyik membuka hadiah, Fran memanggil. Nauren pun menoleh.
“Bagaimana menurutmu? Ini buat menaruh foto-foto kita.” Fran menunjukkan beberapa ambalan kayu yang baru saja dipasangnya di dinding sebelah timur.
Nauren tampak tersenyum ke arah Fran, lalu ia memindai pandangannya kembali pada kami. Ia mencomot Gorden dan juga aku, lalu membawa kami mendekat ke tempat Fran berdiri. Nauren mengulurkan tubuh Gorden kepada Fran, supaya dipasangkannya ke kusen jendela.
“Ini warnanya cocok dengan konsep kamar kita,” ujar Nauren. Fran mengangguk-angguk.
Setelah Nauren membuka lilitan pita dan melepas kotak mika yang di salah satu sisinya terdapat huruf timbul yang terbaca sebagai Floria, ia tersenyum kepadaku. Lalu, ia pun meletakkanku di sebuah ambalan kayu yang berada paling dekat dengan jendela.
“Menggemaskan sekali kaktus itu.”
“Iya, ini dari Flo.”
“Oh,” ujar Fran datar. Gorden sudah selesai ia pasang tapi ia lupa menutupnya saat kemudian Nauren menghambur ke pelukannya dan menariknya ke ranjang yang plastik pelapisnya belum dibuka.
“Beginilah kalau pengantin baru. Aku sama sekali tidak kaget.” Gorden mengoceh dan sambil terus terkikik.
Sungguh menyebalkan, sementara Nauren dan Fran bersenang-senang, aku justru harus berdampingan dengan gorden yang berisik.
Aku selalu berdoa supaya Nauren memindahkanku ke tempat lain, atau kalau tidak, supaya ia lekas mengganti gorden. Sampai entah sudah berapa ratus hari aku telah tinggal dan lupa dengan doa itu. Aku tak ingat kapan tepatnya aku mulai beradaptasi dengan Gorden. Tahu-tahu Nauren sudah mengganti kalender di dinding sebanyak tiga kali.
Dalam waktu selama itu, aku selalu disemprot dan dibersihkan menggunakan sikat sebesar kelingking Nauren secara berkala. Begitupun dengan Gorden, saat mulai berdebu, ia selalu dilepas dari pengaitnya dan dibawa ke kamar mandi oleh Nauren, lalu setelah seharian tak terlihat, ia akan kembali dengan keadaan bersih dan wangi. Nauren memang amat telaten. Di tengah kesibukannya sebagai wanita karir, ia tetap menyempatkan diri untuk memperhatikan kami.
Namun, mungkin karena ditelan kesibukan yang semakin banyak, Nauren tiba-tiba saja berhenti melakukan rutinitas itu. Sudah lama sekali tapi aku tak tahu berapa tepatnya—karena kalender di dinding sudah mati dan Nauren maupun Fran tidak kunjung menggantinya. Dari percakapan terakhir mereka yang kudengar, Nauren telah dipindahkan ke cabang perusahaan yang baru diresmikan, dan Fran tetap bekerja di tempat yang sama tapi berhasil naik jabatan. Kukira, itulah alasan Fran bangun lebih awal dari Nauren, lalu berangkat dengan gerakan serba tergesa. Tak ada adegan sarapan bersama, tak ada adegan Nauren memasangkan dasi untuk Fran. Tak ada adegan Fran mencium kening Nauren. Seringkali Fran juga pulang saat Nauren sudah tertidur lelap.
Sementara Nauren, sebesar apa beban yang harus ia pikul di tempat baru? Ia yang mulanya ceria di setiap keadaan, berangsur layu dari waktu ke waktu. Tak ada lagi ia yang selalu menyapaku setiap kali pulang kerja dan ia yang gemar mencatat hal-hal penting di kertas memo sambil senyum-senyum—dan menempelkannya di sebelahku.
Rutinitasnya menjadi berkelindan antara bangun tidur, berangkat kerja dan tidur lagi. Bahkan pada akhir pekan, saat Fran selalu pergi karena berbagai urusan, Nauren hanya memilih tiduran. Ia tidak beranjak bangun bahkan untuk sekadar membuka jendela. Gorden mulanya selalu mengomel, tapi lama-lama ia hanya diam. Mendengarnya berisik memang menjengkelkan, tapi jika diam begitu, dia tampak kasihan.
“Tumben kau diam, Gor?” selorohku suatu kali.
“Tumben juga kau ngajak ngomong dulu?”
“Apa salahnya?”
“Nggak ada. Itu bagus. Kamu memang harus memulai obrolan dengan yang lain. Meski berduri, kau sebenarnya imut, sayangnya watakmu begitu. Ya pokoknya belajarlah, nanti kalau ada gorden baru kamu harus bisa lebih ramah.”
“Makasih buat pujiannya, tapi … apa maksudmu?”
“Lihatlah, badanku sudah tebal dengan debu, aku jadi sering batuk-batuk.”
“Ya maksudku, kalau mau menggantimu, kenapa Nauren nggak lakukan itu dari dulu? Menurutku, warna toska sepertinya lebih cocok.”
“Sialan kamu.”
“Wah, Gorden bisa mengumpat sekarang.”
“Aku hanya mengatakan apa yang sering mereka katakan akhir-akhir ini.”
***
Aku tak menyangka hari yang disebutkan Gorden terjadi juga. Oleh Nauren, Gorden ditarik dari kusen dan dilipat dengan asal-asalan. Lalu, dijejalkan ke dalam kardus besar bertuliskan: Untuk Donasi. Tak hanya Gorden, tapi seluruh benda yang ada di kamar, kecuali aku. Kukira aku akan dimasukkan terakhir kali oleh Nauren, tapi hingga empat kardus dilakban, aku tetap teronggok di ambalan. Rasanya sesak sekali melihat benda-benda itu dibawa oleh orang-orang berseragam biru. Sebagian besar mereka adalah kado-kado yang dulu dibungkus dan saling bertumpuk, temanku yang sudah ada bersamaku sejak awal. Lebih-lebih Gorden, walau bagaimanapun, dia yang paling dekat denganku.
Dua hari lalu, setelah sekian lama, Nauren menghampiriku. Ia bergeming sambil menatapku. Dan secara pasti, ia menggenggam tubuhku dengan erat, hingga duri-duriku terasa menyusup ke kulitnya. Jika bisa meloloskan diri, tentu akan kulakukan.
Aku hanya bisa berteriak, meskipun usaha itu tetap sia-sia. Nauren melepaskan genggamannya, dan telapak tangannya penuh darah tentu saja. Air matanya jatuh, tapi aku tahu itu bukan karena duri-duriku.
“Kenapa harus kamu dari sekian banyak orang, Flo?” ia berkata pelan.
Dilepasnya syal yang melilit di lehernya, lalu ia gunakan untuk mengusap matanya dan membebat tangannya yang berdarah. Ia tersenyum tipis, lalu melenggang pergi tanpa menoleh meski sekali. Ia tak membanting pintu, tak ada gema yang tertinggal setelah itu. Sesenyap itu caranya meninggalkanku. Ruangan ini benar-benar kosong saat aku pertama kali datang. Dan kini, menjadi kosong pula seperti semula. (*)
Jepara, 25 November 2024.
Retno Ka. Ibu dari seorang anak lelaki. Menyukai hijau, dan laut.

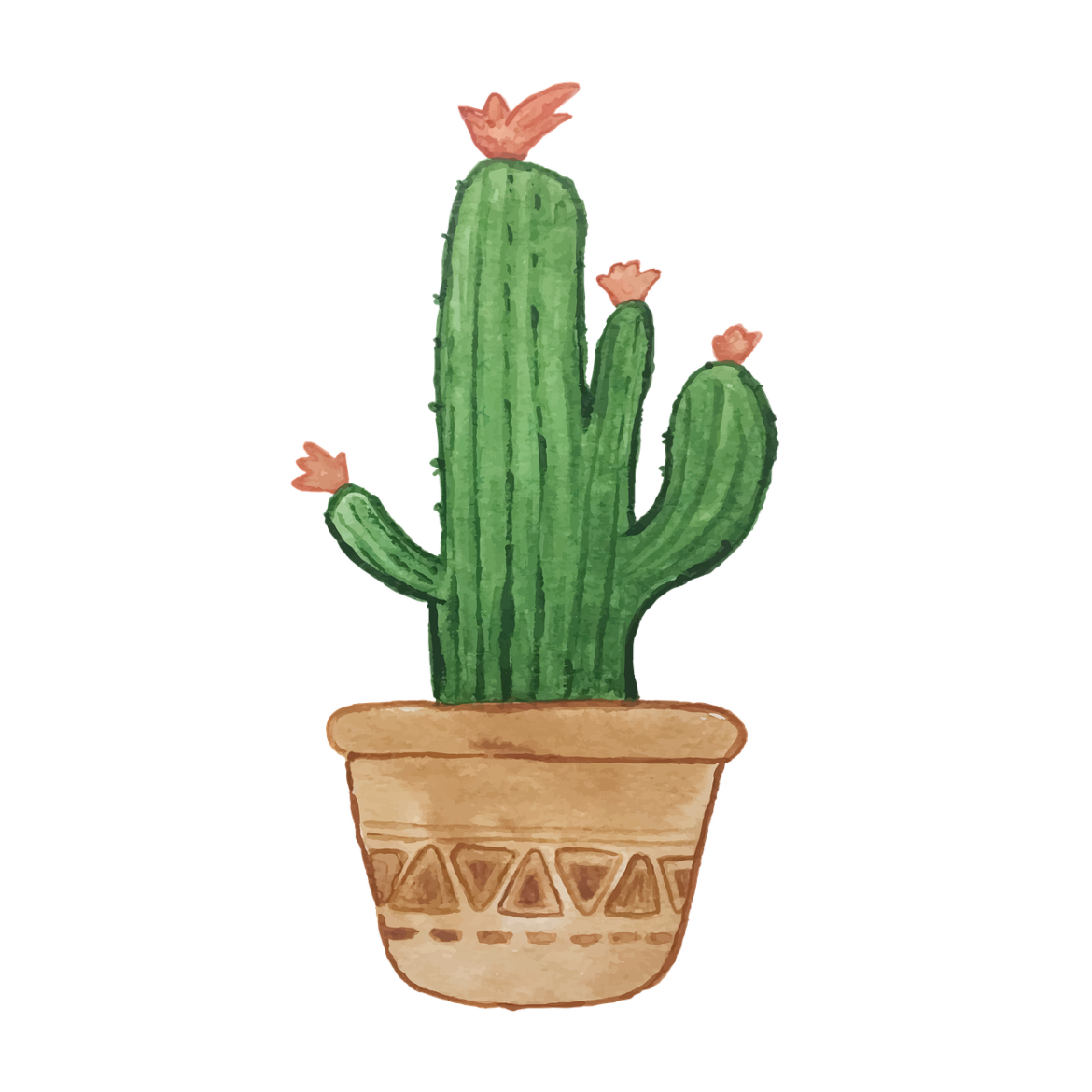



10 thoughts on “Aku dan Ruangan yang Dahulu Kosong”