Geger Geden Dusun Salakbrojo
Inet Wijaya
Dhe Tuo—kakek—pernah bilang, kepala desa Kaligawe harus dari dusun Salakbrojo, kalau tidak nasibnya akan seperti Bau Kadir, tidak dapat lama berkuasa. Menurut kabar angin, Bau Kadir suka berbagi kepada fakir miskin, para janda, dan gelandangan. Namun ternyata pakai duit korupsi, berbondong-bondonglah masyarakat Kaligawe menumbangkan Bau Kadir hingga dipecat jadi kades. Padahal tiada bukti untuk memenjarakan Bau Kadir. Mau bagaimana lagi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Adapula yang nasibnya sakit-sakitan, baru menjabat seumur jagung sudah diambil Gusti Allah.
Selama berdekade kemudian, kades Kaligawe selalu berasal dari dusun Salakbrojo. Tiada yang berminat dari dusun lain. Namun, kini zaman telah berbeda, memori buruk tentang Bau Kadir telah menguap. Menjadi takhayul bagi sebagian orang tapi tidak bagiku. Aku haqqul yakin yang ceritakan Dhe Tuo benar adanya. Jika saja Dhe Tuo masih hidup, beliau pasti akan bilang ciloko karena ada bakal calon kades yang tidak berasal dari dusun Salakbrojo. Berani betul dia menantang ciloko.
Pagi-pagi buta, Rijal bertamu sambil marah-marah sampai anak istriku ketakutan. Katanya Humaidi—calon kades dari dusun lain—membagikan sembako beserta uang seratus ribuan. Ditambah menurut kabar angin, pada saat pemilihan akan ada serangan fajar yang nilainya bisa buat beli beras dan lauk selama seminggu. Terang saja Rijal marah, begitupun denganku. Kami adalah relawan Tad Siroj—calon kades dari dusun Salakbrojo—yang saleh.
“Kotor sekali caranya, Ja!” seru Rijal. Mukanya seperti kepiting rebus kematengan. Alot dan merah.
“Ini ndak bisa dibiarkan. Ciloko. Bisa kalah nanti Tad Siroj,” balasku.
“Lukman pengkhianat, Ja. De’e wong Salakbrojo tapi jadi timsesnya Humaidi. Ngurus-ngurusi suap.”
“Wes. Nanti sore kita ke rumahnya. Tak bujuk e, biar tobat dia.”
Begitu Rijal pamit, istriku menyeret lenganku ke kamar. Sudah pasti dia mau menceramahiku seperti yang sebelum-sebelumnya. Matanya saja sudah menyala seperti induk singa yang anaknya diganggu. Perempuan selalu memikirkan hal-hal yang berlebihan, was-was, dan gampang menyimpulkan sendiri.
“Sudah, tho, Pak. Tidak usah ngurusi sampai begitunya masalah kades. Zaman saiki ngeri, Pak,” terang Rukmini—istriku.
“Wes, Ibuk tidak usah khawatir. Ini urusan wong lanang, Buk. Pokok Ibuk seng tenang.”
“Bapak iki dapat apa tho jadi relawan?”
“Lho, Ibuk ki ndak paham. Iki masalah serius, Buk. Pemimpin itu harus dipilih yang bener, kalau yang ndak bener kepilih ciloko. Wes! Bapak mau siap-siap berangkat kerja.”
Menjelang Magrib, aku dan Rijal ke rumah Lukman. Rijal masih tampak berapi-api, langkahnya lebar-lebar tidak sabar mau melabrak Lukman. Sepanjang perjalanan ia tidak banyak bicara, hanya menanggapiku seperlunya. Belum pernah kulihat Rijal seperti ini, paling banter emosi Rijal meledak dulu waktu sekolah, dia menantang guru agama berduel karena melihat lelaki paruh baya itu melecehkan anak perempuan. Bogem mentahnya begitu saja Rijal daratkan ke muka guru cabul, beruntung Bu Yuli segera melerainya. Guru yang dulu ditaksir Rijal karena cantik, lembut, dan baik hati.
Aku jadi waswas sendiri kalau-kalau Rijal mengajak duel Lukman. Apalagi Lukman orangnya keras hati. Meski begitu separuh dalam diriku pun mendukung Rijal, makanya kakiku begitu enteng menuju rumah Lukman. Biar kena batunya dia coba-coba menjegal calon kades dari Salakbrojo. Aku membayangkan Rijal akan membuat Lukman babak belur, dilihat dari proporsi tubuh saja Lukman kalah jauh. Rijal bertubuh tinggi tegap berisi juga berotot. Mungkin itu efek dari kerjaannya yang sebagai kuli bangunan. Sedangkan Lukman meskipun tinggi, tapi kurus krempeng, dia sedikit ditakuti cuma karena tato naga api yang bertengger di lehernya.
Kulihat Lukman duduk di teras, ia seperti sedang menunggu kami. Kaki kanannya ia tumpukan di paha kiri. Dua jari tangannya mengapit rokok yang sudah separo. Langit sudah berwarna jingga tua, sebentar lagi gelap menjemput. Suasana di sekitar sudah sepi, tengngangi menjadi alasan para orang tua menyuruh anak-anaknya berdiam di rumah. Bahaya, saat tengngangi ada candik olo. “Kelakuanmu itu olo, Man. Jangan diteruskan, ciloko!” seru Rijal begitu sudah di depan Lukman.
“Opo maksudmu? Hah!” balas Lukman.
“Kowe mbagi-mbagi sembako dan duit biar Humaidi kepilih. Kliru, Man. Kowe wong Salakbrojo!”
“Halah ndak usah ribut. Sini maju! Tak layani!”
Darah Rijal yang sudah mendidih tambah meluap ketika ditantang Lukman. Rijal maju, ia memasang kuda-kuda. Lalu dalam hitungan detik bogem mentah telah mendarat di muka Lukman hingga ia tersungkur. Sebelum Lukman bangkit, Rijal sudah mendaratkan bogem kedua di sudut bibir Lukman, membuatnya gagal bangkit.
“Wes! Cukup, Jal.” Aku mencoba melerai melihat Lukman sudah kepayahan meski baru dua kali tonjokan. Rupanya Lukman memanfaatkan hal itu untuk berdiri. Dan saat mataku bertumpu pada Lukman, tiba-tiba Rijal ambruk. Darah bersimbah di tubuhnya. Sementara itu parang di tangan Lukman menjadi semerah darah. Tetes-tetes darah yang berasal dari parang itu membuat tubuhku terpaku. Tak kudengar erangan Rijal yang membuat geger geden dusun Salakbrojo.
Pekalongan, 25 November 2024.
Inet Wijaya. Suka lihat bulan dan baca novel.

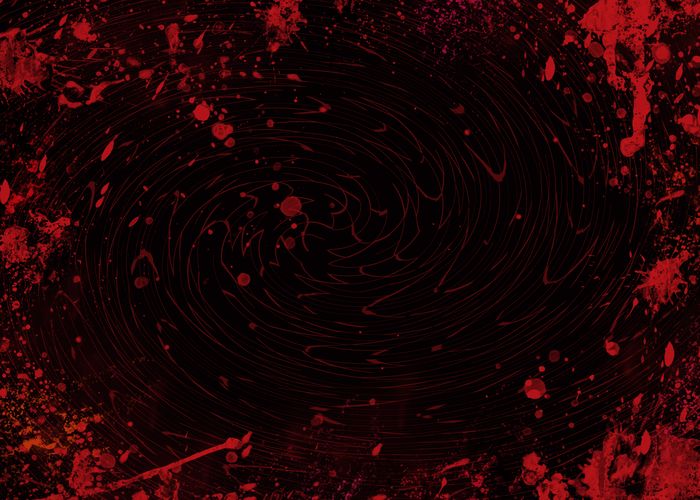



9 thoughts on “Geger Geden Dusun Salakbrojo”