Ketika Hitam Bersemayam
Oleh: Ridwan
Aku dan Herman berteman sejak kecil. Kami telah melewati banyak sekali kenangan indah. Mulai dari berangkat sekolah sama-sama, bermain layangan, berenang di empangnya Pak Kumis yang terkenal garang, bahkan mengaji pun tak pernah kami berangkat masing-masing. Hampir setiap hari, aku tak akan jauh-jauh darinya.
Dia orang yang sangat baik dan pengertian. Aku ingat ketika dulu pernah dijahili anak kampung sebelah, dialah yang membantuku. Mereka–anak-anak kampung sebelah–lari tunggang langgang ketika berhadapan dengannya. Tentu saja, karena postur badannya lebih besar dari anak seusia kami.
Namun, di balik sifatnya yang seperti itu, dia sangat sensitif. Terutama ketika membahas sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Seolah itu adalah hal yang haram dibahas di antara kami berdua. Aku tahu sedikit kenapa dia seperti itu.
Dia pernah bercerita bahwa kehidupannya di rumah sangat lain. Dia merasa sudah tak punya lagi tempat untuk berlindung. Ayah dan ibunya sering kali bertengkar, dan hal itu sangat mempengaruhinya. Tak aneh ketika tak sengaja kulihat di sekujur tubuhnya terdapat memar. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, justru menjelma menjadi tempat yang mengerikan.
Seiring berjalannya waktu, kami berdua tumbuh di jalan yang berbeda. Aku, berkat orang tuaku yang sangat disiplin terhadap ilmu agama, melanjutkan pendidikan di MA, sekolah menengah atas yang berbasis agama. Sedangkan dia, melanjutkan ke sekolah swasta. Kami pun berpisah.
Tiga bulan pertama, kami masih dapat berkomunikasi dan bertemu seusai sekolah. Kami saling menceritakan keseruan kami di sekolah masing-masing. Kudengar dia telah mendapatkan banyak teman. Terlihat dari raut wajahnya, dia sangat menikmati masa mudanya. Aku turut senang.
Bulan demi bulan berlalu. Kehadirannya seakan ditelan waktu. Lenyap tak bersisa. Dia sangat sulit dijumpai. Entah karena sibuk dengan sekolahnya, mungkin. Aku tak tahu. Aku hanya bisa berharap dan berdoa, semoga dia selalu dalam keadaan baik.
***
Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Ujian kenaikan kelas berlangsung empat hari lagi. Dari jauh-jauh hari aku telah mempersiapkan diri untuk ujian ini. Akan kukerahkan semua kemampuanku, agar tak membuat kecewa Ayah dan Ibu.
Aku yang sedang membaca buku, tiba-tiba dipanggil Ibu.
“Nak, tolong belikan ibu garam, ya. Sekalian berasnya,” ucap Ibu seraya memberiku selembar uang lima puluh ribu.
Aku berjalan menuju warung dengan mulut yang tak henti-hentinya merapalkan daftar belanjaan Ibu. Dari kejauhan, kudapati sosok yang sangat kukenal. Itu Herman? Ya, tidak salah lagi! Dia sedang berkumpul dengan segerombolan pemuda. Sambil memainkan alat musik, mereka menyanyi. Sesekali di antara mereka ada yang menyesap rokok–termasuk dia. Aku tak tahu kalau dia sudah berani merokok. Aku berjalan tanpa melihat ke arahnya. Ada rasa sesak di dada.
Akhirnya aku sampai di rumah. Setelah menyerahkan belanjaan pada Ibu, aku kembali ke kamar. Aku melanjutkan aktivitas yang sempat tertunda. Terpikir olehku untuk bisa mengajak Herman kembali ke jalan yang benar. Bukan berarti aku menganggap mereka membawa dampak buruk baginya. Tentu saja, bukan. Kuputuskan untuk menemuinya besok. Aku tak ingin ada penyesalan yang bersemayam di hati.
***
Besoknya, aku kembali ke tempat itu. Tempat Herman dan gerombolannya biasa berkumpul. Pas sekali. Mereka sedang ada di sana. Mereka bernyanyi dan duduk melingkari sebuah botol yang tertutup plastik hitam.
Aku tersentak, menyadari minuman apa yang ada di dalam botol itu. Terlebih lagi ketika melihat Herman sedang bersiap-siap meneguk cairan itu. Ada sesuatu yang mendorongku untuk cepat-cepat menghampirinya.
Dengan sigap, aku menarik tangannya, mengajak dia berjalan denganku. Setelah dirasa cukup jauh, aku berbalik menghadapnya.
“Eh, Man … kau tahu ‘kan apa yang sedang kau lakukan?” tanyaku dengan nada suara cukup tinggi. “Kenapa kau masih mau melakukannya? Itu haram, Man. Kau sendiri pun tahu.” Pecah sudah emosiku. Melihat Herman yang sudah berubah.
“Berisik! Memangnya kau tahu apa tentangku, hah?!” bentaknya, “jangan sok menasehatiku! Aku tahu memang dulu kita teman baik, hidupku tak sepertimu. Kau tak akan tahu rasanya bagaimana!” Nada suaranya meninggi. Sorot matanya seolah-olah menyimpan luka yang teramat dalam. Aku sadar, aku mungkin tidak mengerti apa yang dia rasakan sebenarnya.
“Maafkan aku. Tapi kumohon, jangan seperti ini. Ini membuatku sakit, Man.”
Hening sejenak. Hanya terdengar deru nafas masing-masing.
“Baiklah, Man. Kalau memang sudah seperti ini maumu, aku tak akan menghalangimu. Namun, bila kau ingin kembali seperti dulu, kau tahu siapa yang harus kau tuju.”
Kulangkahkan kaki, pergi menjauh darinya yang masih berdiri mematung. Aku merutuki kebodohanku sebagai teman. Aku merasa gagal, karena seolah-olah sudah membiarkannya jatuh ke lubang yang sangat dalam. Jika sudah begitu, akan sulit lagi mengajaknya kembali.
Namun aku yakin pertolongan Tuhan itu ada. Aku tersadar, tugasku sebagai manusia hanyalah mengajak, bukan memaksakan kehendak. Aku hanya akan terus memanjatkan doa terbaik untuk Herman. (*)
Bandung, 15 Agustus 2021
Ridwan Permana. Pemuda asal Bandung yang kini alhamdulillah sudah resmi menjadi mahasiswa di UIN SGD. Ia sedang mencoba untuk konsisten menulis agar bisa menyalurkan hobi.
Editor: Imas Hanifah N
Gambar: pixabay
Grup FB KCLK
Halaman FB kami
Pengurus dan kontributor
Mengirim/me.jadi penulis tetap di Loker Kata

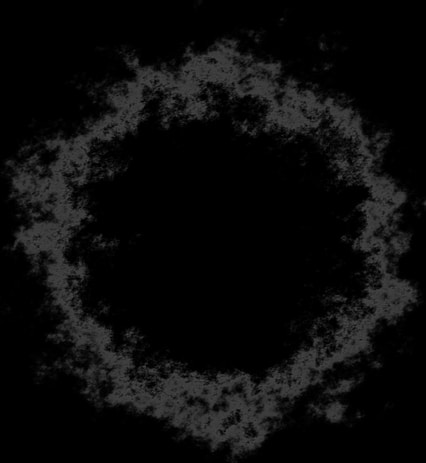



7 thoughts on “Ketika Hitam Bersemayam”