Menggenggam Nasib
Oleh : Elivita Silvia
Wandi bergegas menjejalkan baju-baju ke dalam tas secara sembarang. Ia melirik jam di pergelangan tangannya sesaat, lalu berdecak kesal. Tak ada waktu lagi, lelaki berkulit gelap itu lantas menyambar jaket lusuh di atas kasur dan cepat-cepat keluar dari kamar indekosnya.
Datang dengan tangan kosong, pergi pun dengan tangan kosong. Miris, tapi memang hidup terkadang sesembrono itu. Meski sudah berusaha sekeras mungkin, jika takdir tak mengizinkan hal yang diimpikan tercapai, haruskah mengeluh terus-menerus? Tidak. Wandi bukan orang seperti itu, sudah tahun ketiga ia mengadu nasib di kota metropolitan ini, ia tak boleh pulang dengan tangan hampa. Setidaknya sekarang ia mungkin sedang beruntung, malam tadi kenalannya di kampung dulu, yang sekarang katanya sudah sukses, menawarinya pekerjaan. Berkali-kali kawannya itu meyakinkan bahwa Wandi bisa sukses macam dirinya. Semula ia ragu, apalagi ia yang hanya lulusan sekolah dasar, tak memiliki keahlian apa pun selain mengaduk semen atau mengangkat batu bata, tapi … tak ada salahnya jika ia mencoba, ‘kan? Siapa tahu ini memang jalan yang dipersiapkan Tuhan untuknya.
Sekali lagi Wandi mencocokkan alamat dalam secarik kertas dengan alamat yang tertera di tembok tinggi besar di hadapannya. Tanpa ragu, ia lekas menggeser pagar besi berkarat yang tidak tertutup rapat itu. Ia menarik napas, dan mengembuskannya dengan kasar. Area itu penuh dengan bangkai-bangkai mobil yang sudah berkarat. Ia pun menyusuri tempat itu, mencari keberadaan kawannya yang sudah berjanji menemui Wandi di sana.
Sudah dua jam Wandi berada di tempat rongsokan itu, tetapi nihil, tak ada siapa pun di sana selain dirinya. “Sial!” Wandi berdecak kesal.
Apakah ia ditipu? Tapi buat apa kawannya itu menipu Wandi, toh ia hanya gembel yang tak memiliki apa-apa selain kehidupan nelangsa.
Rasa lapar membuat perutnya semakin panas. Pagi tadi ia pergi dengan terburu-buru, dan lagi ia memang tak memiliki uang bahkan hanya untuk membeli sebatang rokok. Pikirnya ketika ia sampai di tempat tujuan, kawannya akan berbaik hati menawarinya sarapan, meski itu hanya sekadar basa-basi.
Ah, memang tak ada gunanya menggantungkan orang lain. Ada perut yang harus diisi, Wandi memutuskan untuk meninggalkan tempat rongsokan itu.
“Jangan terburu-buru pergi. Bukannya kau ada keperluan di sini?”
Wandi menghela napas, rasanya ia ingin menumpahkan kekesalannya sekarang, tapi ternyata lelaki yang bicara tadi bukan seorang yang Wandi kenal. Siapa dia?
“Duduklah …,” pinta lelaki itu sambil menarik dua buah bangku dari tumpukan bangku di sebelah bangkai mobil.
Wandi mengernyit, tapi ia segera mendekat dan duduk. Wandi hanya diam. Entahlah, mulutnya tiba-tiba menjadi bisu, ia ingin bertanya siapa lelaki itu tapi ia tak bisa melakukannya. Sedang lelaki di sampingnya terus tersenyum sambil mengisap cerutu dan memandangi setumpuk rongsokan di depannya.
“Sudah saatnya hidupmu berubah, Wan. Lagi pula, kau sepertinya penat menjalani kehidupan yang seperti ini, ‘kan?”
Ucapan lelaki itu benar, Wandi hanya menghela napas, menerawang kembali kehidupannya yang benar-benar memuakkan. Ia ingin hidupnya berubah, tapi bagaimana caranya? Cukup lama mereka duduk di sana, Wandi hanya diam mendengarkan sedangkan lelaki itu menceritakan banyak hal, semua hal tentang kehidupan Wandi yang membosankan.
“Sebentar lagi hujan, pergilah.” Lelaki itu lantas bangkit, kemudian melenggang pergi.
Apa-apaan itu? Wandi sama sekali tak paham. Ia hanya membuang-buang waktu berada di sana. Memang benar, ucapan lelaki itu membuatnya tertampar, dan merasa malu karena selama ini ia hanyalah seorang yang gagal. Akan tetapi … menuturkan sesuatu tanpa memberi solusi? Lelaki itu hanya mengejeknya. Wandi akhirnya bergegas pergi. Tadi ia berpikir akan beruntung hari ini, tapi … lihat, ia hanya membuang-buang waktu di tempat sampah itu. Dan kawan Wandi sepertinya tak akan pernah datang. Entahlah, mungkin ia dan kendaraan roda empat yang dibanggakannya sudah ditelan aspal saat menuju kemari.
Hujan mulai turun, Wandi memutuskan untuk mencari tempat berteduh. Ia pun berlari menuju toko yang masih tutup di seberang, ia bisa berlindung di emperannya. Namun naas, Wandi tiba-tiba tertabrak mobil bak terbuka yang melaju kencang.
Tubuh Wandi terasa remuk. Kilauan lampu lima watt yang tiba-tiba menyorot matanya membuatnya mengerjap beberapa kali. Di luar hujan lebat, Wandi mengedarkan pandangan ke sekeliling dengan raut muka kebingungan, dilihatnya sebuah tas berisikan tumpukan baju yang dijejalkan sembarangan tepat berada di atas meja di samping tempat tidur. Ia lantas melirik jam di pergelangannya sesaat, lalu mendesah pelan.
Lelaki itu menggeliat, membalikan posisi tubuh yang benar-benar terasa remuk seperti habis dihantam palu berkali-kali. Mendadak ia terkesiap mendapati sang istri yang masih terlelap di sebelahnya. Dalam kepalanya, tiba-tiba terbayang ingatan saat sang istri melarangnya untuk pergi ke kota, tetapi dirinya tetap bersikeras untuk pergi esok harinya.
Wandi bangun perlahan. Dikecupnya kening sang istri sambil membelai pucuk kepalanya, pelan. Semua terasa aneh. Ia seakan kembali ke masa tiga tahun silam. Masa-masa saat dirinya dengan mantap memutuskan pergi ke kota besar, mengadu nasib demi bisa keluar dari roda kemiskinan yang menjeratnya.
“Mas, jangan tinggalin aku sama Rafa,” ucap sang istri pelan sambil memegang lengan Wandi.
Wandi mematung, pilu tiba-tiba menelusuk di seluruh tubuhnya ketika ia menatap wajah sendu sang istri. Ingatan dalam kepalanya berputar kembali ke masa saat dirinya terlunta-lunta di jalanan ibu kota. Rasa sakit akibat hantaman para preman yang membuat wajahnya babak belur saat ia dikeroyok dan dirampok di sekitar terminal bus bahkan masih bisa ia rasakan sekarang. Juga makian dari mandor tempatnya bekerja sebagai kuli saat ia meminta kasbon demi mengirim uang pada istrinya. Kedua mata Wandi terpejam, napasnya tak beraturan dengan keringat dingin mengucur di seluruh tubuh. Suara klakson dari mobil bak terbuka terdengar berulang-ulang memekakkan telinga. Rasa sakit di seluruh badannya kini pun bertambah berkali lipat.
“Mas Wandi, Mas … bangun … ada apa, Mas?”
Santi, istri Wandi begitu cemas dengan keadaan suaminya. Ia terus berusaha membangunkan sang suami yang masih setengah sadar. Ibu satu anak itu mengguncang-guncang tubuh dan sesekali menepuk kedua pipi Wandi.
Wandi akhirnya terbangun, ia langsung membuka kedua mata dan gegas bangkit berdiri. Lelaki itu tampak linglung, ia memperhatikan sekeliling. Kasur bersprei lusuh dengan satu lemari usang di sampingnya, langit-langit penuh debu … dan, seorang wanita yang jelas tetap cantik meski tanpa polesan make up berdiri tepat di hadapan Wandi.
Wandi mengerjap dan mengusap mukanya beberapa kali, memastikan semua yang ada di sekitarnya benar-benar nyata. Benarkah ia berada di kamarnya? Di rumahnya yang berada di kampung? Lalu, pekerjaannya di kota, kawan yang ia tunggu tapi tak kunjung datang, pak tua yang berceracau tak jelas di tempat rongsokan, juga mobil bak terbuka yang menabraknya? Apa semua itu hanya mimpi? Tidak … semua itu terasa begitu jelas dan nyata.
Santi kembali menepuk kedua pipi suaminya, ia jelas sangat cemas melihat lelaki di hadapannya begitu pucat.
“Mas, kamu kenapa?”
Wandi terdiam sesaat, dan cepat-cepat menggeleng. Ini bukan mimpi, bahkan hal-hal yang ia lalui sebelum ini juga bukan mimpi. Ia yakin itu. Gelang jam di pergelangan tangannya … gelang jam itu ia beli setelah mendapat upah saat pertama kali bekerja di kota. Lelaki itu mengusap mukanya, lantas memeluk istrinya dengan erat.
Langit mulai terang, Wandi duduk di teras sambil menyeruput segelas kopi yang masih mengepul. Sang istri yang hendak mengantar putra mereka ke PAUD mencium tangan Wandi, dan berpamitan pergi. Lelaki itu berkali mengembuskan napas lega. Kehidupan seperti ini begitu sempurna. Meski ia yakin semua ingatan yang ada di kepalanya bukanlah mimpi belaka, ia tak lagi peduli, semua baik-baik saja sekarang, dan akan begitu seterusnya.
Tak lama, terdengar suara jeritan sang istri. Wandi terkejut, ia pun langsung berlari menyusulnya.
Wandi mematung dengan lidah kelu. Beberapa orang berkerumun di tengah jalan. Putra semata wayang Wandi, tergeletak berlumuran darah di pangkuan Santi yang menangis histeris. Ia tertabrak mobil bak terbuka yang melintas. Suara tangis Santi terus menggema beradu dengan hujan yang tiba-tiba turun dengan lebat.
Wandi yang tetap mematung dengan lidah kelu kini mendadak berada di rumahnya. Di luar hujan masih lebat, suara tangis menggema di seisi rumah yang penuh dengan pelayat. Wandi menatap nanar jenazah beralaskan tikar yang tertutup kain jarik di hadapannya. Sambil menguatkan hati, Wandi mendekat, sedikit membungkuk dan menyibak pelan kain jarik tersebut.
Jantung Wandi terasa mendadak berhenti. Dengan tubuh yang gemetaran, ia melirik ke arah santi dan putranya yang menangis di samping jenazah itu, jenazah dirinya sendiri.
Hujan turun semakin lebat di luar, begitu pun dengan untaian doa yang dilantunkan para pelayat. Dengan gontai, Wandi memilih pergi keluar, menuju jalanan. Ia benar-benar tak percaya melihat tubuhnya terbaring tak bernyawa seperti itu. Kedua kakinya terasa lemas, pikirannya kacau. Tiba-tiba, terbayang sosok wajah anak dan istrinya yang begitu sedih, berdiri di ambang pintu rumah menantikan kepulangan Wandi dari kota. Tanpa sadar, sebuah mobil bak terbuka bergerak cepat menuju ke arahnya. Wandi tak menghiraukan suara klakson yang berbunyi berkali-kali. Tubuh Wandi akhirnya terpental, tertabrak mobil itu.
Lamat-lamat, Wandi mendengar suara tangis sang istri dari luar ruangan tempatnya terbaring. Di sebelahnya, lelaki yang Wandi temui di tempat rongsokan duduk sambil menyeringai. (*)
Elivita Silvia. Perempuan berdarah jawa, lahir di bulan feberuari tahun 2000. Bertempat tinggal di Batang Jawa tengah, sudah sejak kecil gemar membaca. Mimpinya memiliki buku solo yang terpajang di toko-toko buku besar di seluruh Indonesia. Penulis biasa aktif di sosial media Facebook bernama Jeje, dan Instagram Jeevita_21.
Editor : Devin Elysia Dhywinanda
Grup FB KCLK
Halaman FB Kami
Pengurus dan kontributor
Mengirim/Menjadi penulis tetap di Loker Kata

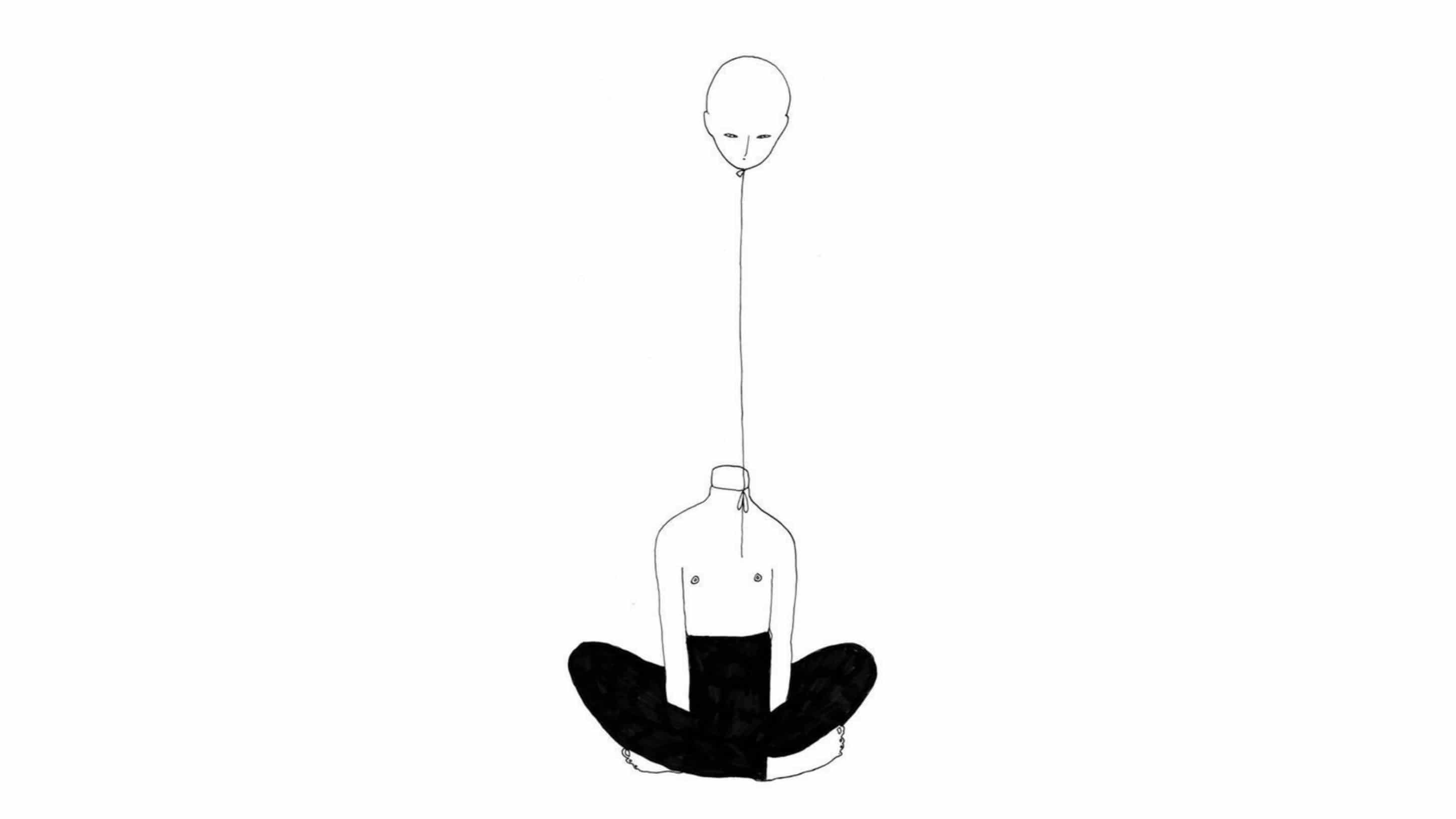



11 thoughts on “Menggenggam Nasib”