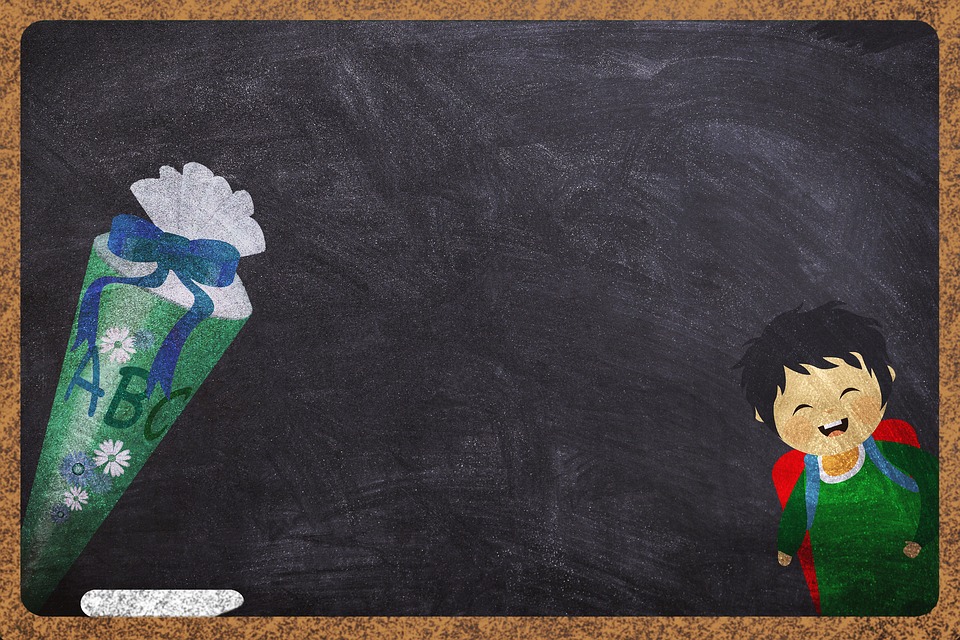Saat Hilman Datang Mencuri
Oleh : Tri Wahyu Utami
Hilman jera. Ia takut pergi ke sekolah setelah Jaka, teman sekelasnya dulu, menangkap basah dirinya yang hendak mencuri sesuatu saat jam istirahat berlangsung. Kala itu Hilman kurang berhati-hati, dan terlalu lamban bertindak. Padahal seperti biasanya, ruang kelas tempat ia mencuri tampak sepi sebab sebagian besar siswa—yang juga pernah menjadi teman belajarnya sebelum ia putus sekolah—sedang sibuk mengisi perut di kantin. Sebagiannya lagi sedang asyik berlarian di lapangan. Ada yang bermain bola, berkejaran ke sana kemari mencari teman yang bersembunyi, dan ada juga yang berputar mengelilingi lapangan dengan melontarkan kalimat makian. Sasarannya, sudah tentu seorang guru yang sedang berdiri di pinggir lapangan sambil menenteng buku “catatan pelanggaran siswa”.
Salah satu yang berlari mengelilingi lapangan dengan raut muka kesal, adalah Jaka. Hilman tak heran dengan hal itu, tapi teriakan Jaka ketika memergoki ia yang tengah berdiri di balik jendela kelas, langsung membuatnya terkejut.
“Hilman, tunggu!” cegahnya sambil memegang lengan bocah itu. “Mau ke mana kamu?”
“Pulang,” jawab Hilman singkat.
“Kenapa?”
“A—apa maksudmu kenapa? Aku memang ingin pulang.”
Jaka terkekeh pelan. “Jangan bohong. Bukannya tadi kamu—”
“Sssttt! Jangan berisik. Nanti kalau ada yang dengar bagaimana? Apa kamu tidak kasihan sama aku?” ucap Hilman panjang lebar. Tangan kirinya langsung menyeret paksa lengan Jaka untuk menjauh dari tembok kelas bercat putih itu.
Di dekat semak-semak berduri yang bersebelahan dengan rumah seorang tukang kebun, yang juga penjaga sekolah, mereka melanjutkan obrolan.
“Kalau takut ketahuan, kenapa masih nekat kemari?” tanya Jaka, yang sebetulnya lebih terdengar sebagai ejekan bagi Hilman. Jadi, ia tak menggubrisnya sama sekali dan malah balik bertanya kepada bocah berambut keriting itu.
“Lalu kamu sendiri kenapa ke sini? Bukannya kamu sedang dihukum sama Pak Bas? Aku sempat melihatnya tadi,” sindirnya tak mau kalah.
“Iya. Memang menyebalkan betul Pak Bas itu. Lupa tidak mengerjakan PR saja sudah menghukum kami seberat ini. Dikira tidak capai apa berkeliling lapangan seperti itu? Huft!”
Alih-alih merasa simpati atas apa yang menimpa Jaka, Hilman justru tersenyum miring kemudian berkata, “Memangnya sudah berapa kali kamu tidak mengerjakan PR?”
“Dua kali, Man. Eh … sepertinya tiga kali. Hehe ….”
“Lalu kenapa tidak pakai dasi?”
“Dasi? Ooo … ketinggalan di rumah,” selanya sambil memasang wajah malu. “Tadi pagi aku terlambat bangun, jadi berpakaian pun terburu-buru sampai lupa tidak memakai dasi. Eh, sampai sekolah ternyata upacaranya sudah dimulai.”
“Hah? Jadi kamu tidak ikut upacara?”
“Hm, sudahlah tidak usah membahasnya lagi,” potong Jaka. “O ya, Man. Kemarin kamu ke sini juga, kan?”
“Iya. Bagaimana kamu tahu? Sepertinya kemarin aku tidak melihatmu ada di kelas saat jam istirahat.”
“Memang iya. Bukan aku yang melihatmu celingukan seperti tadi, tapi Ria.”
“Ria?” Mengetahui ada teman lain yang sudah menyaksikan perbuatannya, Hilman jadi salah tingkah. Ia takut kalau sampai Ria membuka mulut; menyebarkan berita tentangnya kepada semua orang, terlebih pada wali kelasnya yang dulu, Bu Nuni. Sebab jika sampai itu terjadi, keinginannya untuk kembali bersekolah bisa pupus begitu saja. Bahkan mungkin, Ibu akan mengurungkan niat untuk memberikannya hadiah—buku-buku pelajaran untuk ia pelajari di rumah.
Hadiah itu hanya bisa Hilman dapatkan jika ia menurut apa kata Ibu, dan sialnya, ia telah melanggar hal yang paling wanita itu larang sebelumnya. Bahkan sampai detik ini.
Ibu tahu betul keinginan anaknya. Tapi menghadapi Bu Nuni yang juga menginginkan agar Hilman kembali bersekolah, sementara kesulitan hidup yang mereka hadapi kian hari kian bertambah, bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Jadi ia menghindar, dan menjauhkan Hilman dari risiko semacam itu. Dari kunjungan Bu Nuni ke rumah mereka, yang bisa saja terjadi jika anak lelakinya itu berulah yang tidak-tidak.
“Ibu janji Man, akan membelikanmu buku-buku itu. Nanti, kalau Ibu sudah punya cukup uang untuk membelinya,” ucap Ibu di suatu pagi usai Bu Nuni menemui keduanya dan membujuk Ibu agar mau menerima bantuan darinya. Namun, seperti yang sudah-sudah, Ibu menolak sebab tidak ingin berutang budi pada siapa pun. Melihat Hilman putus sekolah memang hal yang menyedihkan, tapi berpangku tangan kepada orang lain juga bukan sesuatu yang ia inginkan.
“Ibu tidak bohong, kan?” tanya si anak memastikan keseriusan ibunya.
“Tidak, asal kamu menurut dan tidak bertingkah buruk seperti kemarin-kemarin.”
Sebenarnya Hilman merasa heran terhadap Ibu yang menganggapnya berkelakuan buruk. Ia memang bukan lagi murid di sekolah itu. Namun, benarkah demikian? Benarkah jika mencuri catatan pelajaran yang tertulis di papan tulis adalah perilaku buruk?
Ah, kalau saja bisa, Hilman juga tidak mau seperti itu. Menyulitkan sang Ibu dan membuat orang lain menatap melas wajahnya usai mereka mengetahui bahwa si pencuri catatan adalah anak yang malang. Seorang bocah yatim yang sudah putus sekolah semenjak dua tahun silam, dan yang belakangan ini memiliki hobi baru: menyambangi sekolah dengan mengendap-endap demi bisa menuliskan sesuatu di buku tulis kesayangannya.
“Ibumu bisa marah kalau tahu hal ini. Jadi, kenapa tidak meminjam buku catatanku saja?” saran Jaka. Namun lagi-lagi, sesering apa pun temannya itu berucap demikian, Hilman selalu menolak. Bukan tanpa alasan, melainkan karena ia tahu betul buku catatan macam apa yang Jaka maksudkan tadi. Jangankan mencatat materi pelajaran, mengerjakan tugas saja jarang kamu lakukan, Jak! batin Hilman, sampai kemudian ia bersikukuh untuk tetap pergi ke sekolah. Di jam istirahat, dan ketika kelas yang ia tuju dalam keadaan sepi.
***
Sudah sepekan semenjak Jaka mengajaknya mencari bambu di pekarangan tetangga, Hilman tak pernah datang lagi ke sekolah. Ibu sakit dan jadilah ia yang menyelesaikan semua pekerjaan rumah seorang diri. Bocah itu pun tak punya banyak waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Padahal, suasana kampung tempat ia tinggal sedang ramai-ramainya.
Di sepanjang jalan depan rumah, berjajaran tiang-tiang bendera dan segala pernak-pernik beraneka rupa yang didominasi warna merah-putih. Memasuki bulan Agustus, kampung itu memang selalu ramai oleh beragam kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan. Namun tahun ini berbeda, Hilman tak bisa lagi mengikuti kegiatan itu seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Maaf ya, Man. Gara-gara Ibu, kamu jadi tidak ikut lomba.”
Hilman menoleh, lantas menaruh pelan bukunya ke atas meja. Kemudian didekatinya sang Ibu yang sedang terbaring lemah di atas kasur.
“Tidak apa-apa, Bu. Hilman juga malas ikut. Lombanya itu-itu saja,” kilahnya sambil memijiti kaki Ibu. Sebetulnya suasana hati Hilman sedang tidak baik dan ia mulai cemas dengan hal buruk yang terus membayang di benaknya.
Jika aku tidak meminta hadiah itu lagi, Ibu akan segera sembuh, bukan?
***
Bersama Jaka yang sedang sibuk memasang dasi, Hilman mematut diri di depan cermin dengan wajah berseri-seri. Ibunya yang sakit sudah sembuh dan siap menantikan anaknya berpawai ria di depan rumah.
Saat itu adalah minggu keempat bulan Agustus. Kampung tempat mereka tinggal sedang mengadakan pawai budaya, dan kali ini, Hilman ikut serta menjadi salah satu pemegang spanduk. Seperti Jaka, ia juga mengenakan seragam merah-putih. Lengkap dengan atribut yang biasa dipakai siswa sekolah untuk mengikuti upacara bendera.
“Tahun depan, aku mau jadi penonton saja,” bisik Jaka sebelum pawai dimulai.
“Kenapa?” tanya Hilman. Sedikit terkejut dengan hal yang temannya katakan barusan.
“Rasanya malas saja berbaris seperti ini dengan adik kelas.”
“Apa kamu bilang? Adik kelas?”
Ditinjunya perlahan lengan Jaka hingga bocah itu tertawa terpingkal-pingkal. Hilman tahu itu hanya candaan, yang justru akan membuatnya semakin bersemangat meraih cita-cita.
Tahun ajaran baru nanti, Ibu akan mendaftarkan Hilman sebagai siswa baru di sekolah. Jaka senang sekali mendengarnya. Begitu pun Hilman yang sudah tak sabar lagi menanti hari itu tiba. Ah, lega betul rasanya. Ibu memang belum memberikannya hadiah sederhana yang pernah ia minta. Tapi Ibu menepati janjinya. Janji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Berjuang segenap hati demi tercapainya impian sang buah hati.(*)
Malang, 31 Agustus 2019
Tri Wahyu Utami, penulis asal Malang yang mulai aktif menulis sejak Agustus 2017. Beberapa karyanya dimuat dalam antologi bersama penulis lain, yaitu antologi Urband Legend (Jejak Publisher), Kata-Kata Senyap (Jejak Publisher), 26 Cerita untuk Anak Bangsa (Intishar Publishing), One Happiness (Kars Publisher), Kisah Tengah Malam: 13 Purnama dan Orang-Orang Bermata Kelam (Hazerain Publisher), Warisan Ibu dan Anak-Anak Pemerah Susu (Koppand, Karos Publisher), dan Tanda Tanya (Jejak Publisher).
Grup FB KCLK
Halaman FB Kami
Pengurus dan kontributor
Mengirim/Menjadi penulis tetap di Loker Kata