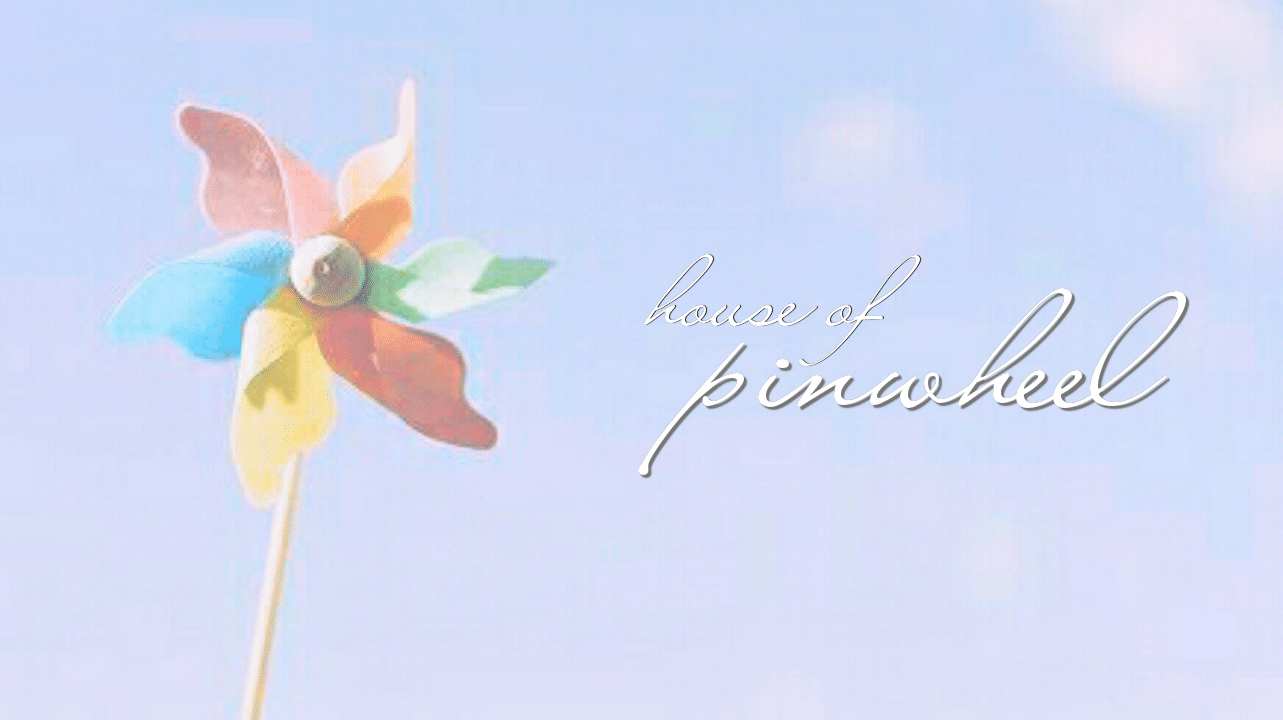House of Pinwheel
Oleh: Devin Elysia Dhywinanda
Risa rindu pada puluhan kincir angin sederhana yang menempati sudut rumah lamanya. Gadis bermata bulat itu ingat, dia selalu mengajak Ibu—juga Ayah—untuk duduk di bawah pohon trembesi yang katanya berumur lebih dari tiga puluh tahun. Ibu bakal menggelar tikar, menyajikan camilan di samping Risa serta Ayah, dan mereka akan membicarakan banyak hal—anak-anak jahil yang tinggal di rumah abu-abu ujung jalan atau guguran daun trembesi yang tidak habis-habis meski telah disapu berulang kali, misalnya—sambil membuat kincir angin dari kertas origami.
Ayah jarang membahas pekerjaannya; dia hanya tertawa, menggoda Risa perihal kemungkinan putrinya menyukai salah satu dari anak-anak jahil itu, yang dibalas dengan pukulan ringan di bahu pegawai kantoran tersebut. Risa akan berpura-pura marah seraya melipat kedua tangan, lantas, setelah tawa Ibu terdengar, gadis berusia sepuluh tahun itu pun ikut-ikutan tergelak.
“Kita harus menyelesaikan kincir angin ini, lalu memasangnya di setiap sudut rumah. Dan lagi, hari ini anginnya sangat kencang, ‘kan?”
Mereka pun melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Lantas, setelah rampung, hasta karya mereka bakal ditempatkan di berbagai sudut rumah, bersama kincir angin lain yang telah dipasang sebelumnya: pagar bambu, ruang keluarga, atau jendela kamarnya sendiri. Jumlahnya kira-kira lebih dari lima puluh lebih sampai-sampai para tetangga menjuluki rumah mereka sebagai Rumah Kincir Angin—sesuatu yang tidak Risa temukan dari rumah barunya.
“Risa rindu rumah.”
Ketika mengatakan hal itu, Ibu berhenti memasak, meraih bahu Risa, lantas berkata bahwa di mana pun tempatnya, asal bersama keluarga, maka mereka telah berada di rumah. Kala itu, Risa menerawang ke luar jendela, memperhatikan korden tipis yang melambai ditiup angin, lantas berkata, “Di sini tidak ada kincir angin, Bu, seperti di rumah kita. Padahal, dulu, kita selalu membuat kincir angin dan memasangnya di setiap sudut rumah.”
Selengkung senyum tercipta di wajah lelah Ibu ketika berkata, “Baiklah. Pulang kerja nanti, Ibu akan membelikan Risa kincir angin. Oke?”
Intonasi Ibu sangat lembut, tidak menunjukkan bahwa dia menganggap permintaan Risa kekanakan. Akan tetapi, Risa melihatnya dengan jelas … dan itu menyakitkan. Padahal, keinginan Risa untuk pulang dan bertemu puluhan kincir angin miliknya didasari oleh rumah baru yang terkesan sangat lengang. Dulu, kendati Ibu sibuk membersihkan rumah dan Ayah pergi bekerja, Risa tidak merasa sepi, sebab kincir angin itu selalu berputar, mengingatkan Risa pada apa yang mereka ceritakan di bawah pohon trembesi. Mereka selalu membawa keramaian magis yang membuat Risa ingat bahwa dia berada di rumah, bersama keluarganya.
Akan tetapi, sejak pindah, rumah barunya benar-benar menyisakan lengang—terlebih Ibu menjadi sibuk bekerja di luar; Ayah tidak kunjung datang—dan itu membuat Risa kesepian.
Risa pernah bertanya tentang perubahan tersebut, yang dijawab Ibu bahwa semua berubah karena memang waktunya berubah. Kenapa bisa begitu, Ibu menjawab, “Dunia ini dinamis, Risa. Risa bahkan telah berubah bila dibandingkan Risa setahun lalu, ‘kan? Ini hanya masalah pemahaman … dan Risa akan memahaminya saat sudah dewasa.”
Apa hal itu juga berlaku dengan rumah serta keluarga, Risa bertanya, yang dijawab oleh Ibu: ya. “Kalau begitu, apakah keluarga bisa disebut keluarga tanpa adanya Ayah?”
Ibu bergeming sejenak, menghela napas, lantas menjawab, “Ya. Toh, Risa dan Ibu saling menyayangi satu sama lain, jadi kita berdua saja sudah bisa disebut keluarga. Dan, itu berarti kita juga berada di rumah. Risa paham?”
“Paham,” jawab Risa ragu. “Lalu, apa itu berarti Ayah sudah tidak menyayangi kita lagi?”
Ibu merapikan seragam Risa. “Ayah masih sayang kita, kok, meski dia tidak di sini, seperti saat Ayah pergi bekerja dulu.”
“Apa Ayah tidak rindu pada rumah?”
“Berbagai hal berubah, Risa, ingat?”
Risa menunduk. “Apa suatu hari Ibu akan berubah, seperti Ayah?”
Ada jeda sebelum Ibu menggeleng lemah. “Tidak. Tentu tidak.”
Setelah itu, Ibu kembali sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan Risa memilih menyandarkan kepala di birai jendela. Lagi-lagi sunyi dan dia seketika teringat pada kincir anginnya yang berputar saat dia belajar; saat Ibu memasak; saat Ayah pulang dan berselonjor di ruang tamu; bersamaan dengan segala aktivitas di rumah lamanya. Seseorang pernah berkata bahwa kincir angin merupakan simbol penantian, sebab dia hanya akan diam dan baru berputar ketika tertiup aliran udara. Akan tetapi bagi Risa sendiri, kincir angin yang berputar dinamis serupa tanda bahwa semua baik-baik saja—tidak dalam keadaan badai yang mampu merusak kertas atau batang bambunya; tidak dalam kepasifan alam yang memaksanya ikut-ikutan diam.
Ia merupakan representasi sempurna dari “keluarga” dan, lebih lanjut, sebuah rumah … sebuah perubahan aneh yang tidak dapat diterima Risa.
Jadi, ketika Ibu membawakan sepuluh kincir angin mainan di suatu sore yang murung, Risa menerima dan menempatkannya di sudut-sudut tersunyi rumah tersebut dengan canggung: kamarnya, kamar Ibu, ruang keluarga, dapur, dan ruang tamu. Sambil meluruskan kaki dan mengeluarkan makan malam, Ibu bercerita, “Ibu hampir lupa membelinya. Untungnya di dekat kompleks perumahan kita ada yang jual, jadi Ibu langsung beli banyak sekalian, biar Risamerasa nyaman sama rumah ini.”
Risa mengangguk pelan, berharap apa yang dikatakan Ibu menjadi kenyataan.
Akan tetapi, seminggu kemudian, rumah barunya masih saja lengang. Dingin. Risa selalu meminta Ibu untuk membawa kincir angin baru dengan dalih masih ada sudut kosong di rumah mereka, membikin Ibu mengernyitkan dahi begitu sadar telah membeli empat puluh benda serupa dalam kurung waktu seminggu. “Masih kurang, Risa?”
Risa bingung mesti menjawab apa, jadi dia hanya mengangguk, membiarkan ketidaknyamanan merambat begitu memahami bahwa kincir angina yang dibelikan Ibu hanya berputar, tidak bercerita perihal keseharian Risa di sekolah baru, Ibu yang kerap tidur lebih awal karena kelelahan, atau alasan Ayah tidak disergap kerinduan serta keinginan untuk pulang. Ia memang berputar dinamis, tetapi tanpa arti—tidak memberikan suasana “rumah”, apalagi keluarga—dan itu membuat Risa frustrasi. Rutinitas merangkai kincir angin di bawah pohon trembesi kembali terbayang dan kian memburuk setiap harinya sampai-sampai dia memberanikan diri menggamit lengan Ibu, berkata, “Risa rindu rumah, Bu.”
Ibu kentara lelah saat menjawab, “Ibu, ‘kan, sudah bilang: selama kita bersama, di mana pun tempatnya, itu dapat disebut sebagai rumah. Ibu juga sudah menuruti permintaanmu untuk membeli kincir angin.” Ibu menahan napas. “Apa itu masih kurang, Risa?”
“Kincir anginnya … berbeda dengan yang di rumah kita dulu, Bu,” jawab Risa setengah takut. Kendati sedikit memahami kesibukan Ibu setelah pindah ke sini, juga permintaan anehnya yang datang terus-terusan, tetapi Risa sadar harus mengatakan hal ini atau dia akan dijepit kesunyian lagi, “Dulu, kita membuatnya bersama-sama, di bawah pohon trembesi—Risa ingin kincir angin yang seperti itu. Kincir angin yang Ibu berikan memang tahan lama, beda sekali dengan milik kita yang harus diganti seminggu sekali, tetapi Risa tetap ingin yang seperti dulu.”
“Apa Ibu harus kembali ke rumah dan membawakan kincir angin itu agar Risa betah di sini?”
Risa menundukkan kepala.
“Kalau iya, Ibu akan melakukannya untuk Risa … supaya Risa juga nyaman tinggal di sini. Tapi, Risa harus jujur, apakah alasan sesungguhnya Risa ingin pulang karena merindukan Ayah?”
Risa menggeleng pelan.
“Ibu menyayangi Risa dan, walaupun tidak ada Ayah, kita adalah keluarga. Ini rumah kita, Risa, dan kita harus beradaptasi dengannya. Semua berubah dan kita juga harus mengikuti perubahan tersebut. Ibu tidak memaksa. Ibu akan menuruti kemauan Risa … karena lambat laun Risa pasti akan terbiasa.”
Risa memainkan jemarinya, menahan mulutnya untuk tidak berkata bahwa Ibu telah salah paham.
“Tapi, kita juga harus saling membiasakan diri. Ya?”
“Bukan begitu, Bu …,”
Ibu hanya belum mengerti bahwa, meski berat, Risa sudah menerima keabsenan Ayah di tempat ini. Ibu hanya belum memahami bahwa Risa merindukan puluhan kincir angin yang berputar, menceritakan ulang semua pembicaraan, segala kenangan, sehingga Risa bisa merasakan sesuatu bernama kasih sayang dan kehangatan. Ibu hanya belum mengetahui bahwa kincir angin itu—beserta sekian kisah yang terlontar ketika origami dilipat, dibentuk sedemikian rupa, lantas direkatkan di batang bambu—punya nilai yang amat berharga, yang serupa dengan makna keluarga … dan rumah itu sendiri.
“Ibu tidak perlu membeli kincir angin lagi. Risa tidak butuh itu semua. Gantinya, ayo kita membuat kincir angin yang baru. Bersama-sama. Di mana saja, kapan saja, yang penting Ibu longgar, dan kita akan memasangnya di setiap sudut rumah.” Risa melanjutkan dengan ragu, “Jadi, kita bisa pulang ke rumah kita. Ya, Bu?” (*)
[*] Terinspirasi dari filosofi kincir angin dalam lagu Seventeen – Pinwheel yang diasosiasikan sebagai tempat untuk pulang.
Devin Elysia Dhywinanda adalah gadis AB hasil hibridisasi dunia Wibu dan Koriya yang lahir di Ponorogo, 10 Agustus 2001.
Grup FB KCLK
Halaman FB Kami
Pengurus dan kontributor
Mengirim/Menjadi penulis tetap di Loker Kata